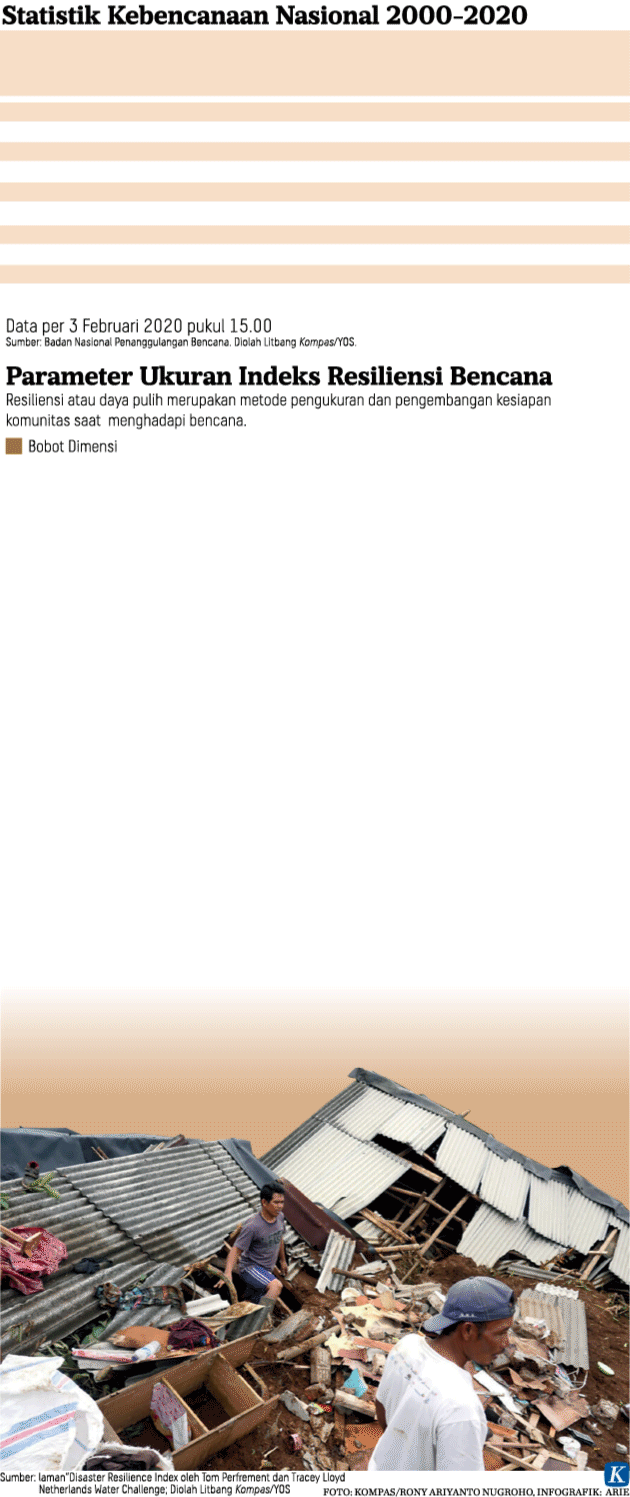Sebagai negara yang memiliki potensi kerawanan bencana, manajemen bencana menjadi satu hal yang penting dilakukan di Indonesia. Pengurangan risiko bencana perlu bergeser pada peningkatan resiliensi atau daya pulih penduduk.
Konsep resiliensi bencana memiliki posisi penting dalam manajemen bencana di dunia. Menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction, resiliensi merupakan kemampuan suatu sistem, komunitas, atau masyarakat yang terpapar bahaya untuk melawan, menyerap, menampung, dan pulih dari dampak bahaya secara tepat waktu serta efisien.
Proses tersebut berlanjut melalui pelestarian dan pemulihan struktur serta fungsi dasar yang penting dalam usaha pulih kembali. Resiliensi memfokuskan investasi pada peningkatan kemampuan suatu wilayah secara keseluruhan untuk mendukung masyarakat tetap kuat dalam berbagai keadaan.
Penilaian resiliensi wilayah terhadap bencana penting dilakukan untuk mengetahui kesiapan yang ada yang digunakan sebagai dasar perumusan arahan adaptasi dan mitigasi lanjutan. Resiliensi menjadi titik kunci untuk mengembalikan kondisi masyarakat setelah terpapar bencana.
Setidaknya ada tiga faktor yang menjelaskan urgensi perumusan resiliensi di Indonesia dalam perspektif pengurangan bencana. Faktor pertama adalah tingkat risiko bencana. Di Indonesia, tingkat risiko bencana tergolong tinggi.
Sebagai gambaran, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selama dua dekade terakhir ada 24.222 kejadian bencana alam, mulai dari hidrometeorologi hingga tektonik. Total korban meninggal akibat bencana sejak tahun 2000 hingga Januari 2020 mencapai 188.854 jiwa. Adapun jumlah korban lainnya mencapai lebih dari 47 juta jiwa.
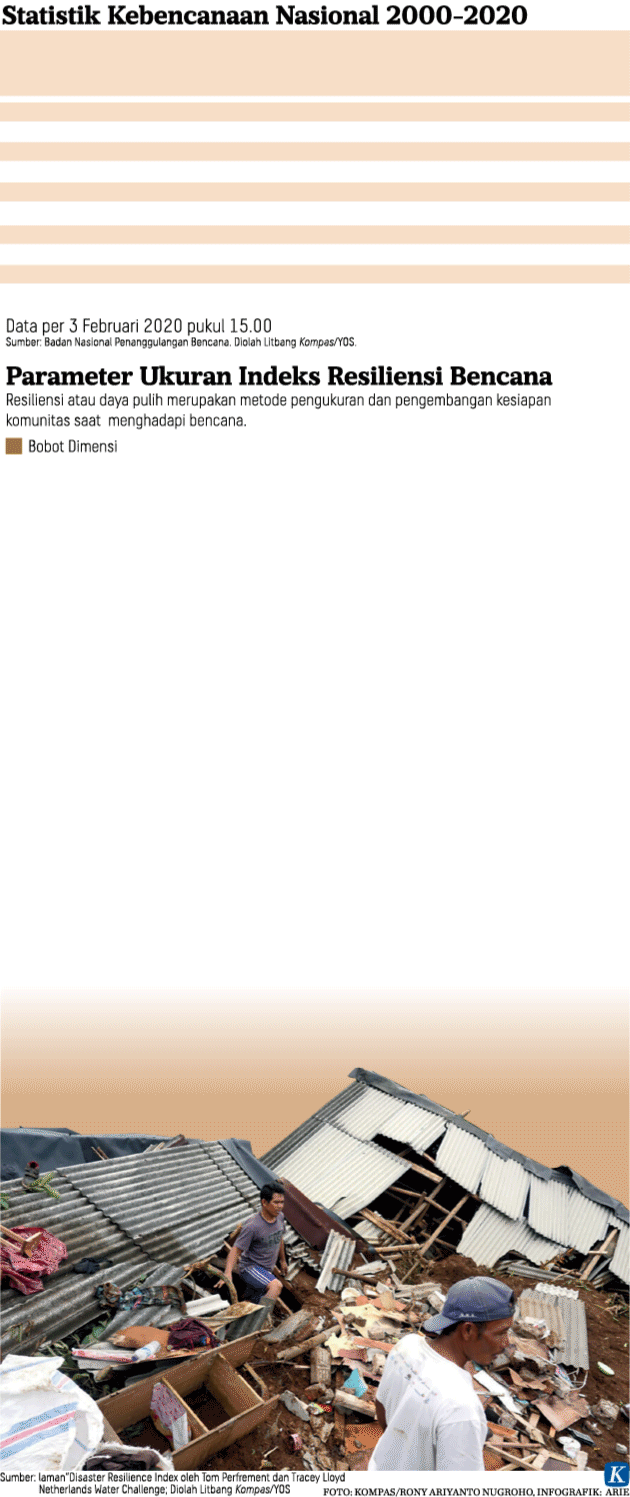
Status kerentanan
Faktor berikutnya ialah kerawanan bencana. Upaya membangun indeks resiliensi tak cukup dengan melihat banyaknya kejadian bencana atau fakta tentang sistem pembiayaan bencana di Indonesia. Langkah berikutnya adalah menyadari Indonesia merupakan negara dengan sumber bencana beragam.
Kerawanan bencana secara nasional mempertimbangkan posisi Indonesia yang berada di jalur cincin api dan batas pertemuan tiga lempeng besar dunia. Konsekuensi kondisi ini ialah ancaman gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung api. Wilayah Indonesia memiliki enam zona subduksi dengan 13 segmentasi megathrust dan 295 segmen sesar aktif. Segmentasi megathrust meliputi Mentawai- Pagai, Enggano, Selat Sunda, barat-tengah Jawa, timur Jawa, Sumba, Aceh-Andaman, Nias- Simeulue, Batu, Mentawai-Siberut, utara Sulawesi, Filipina, dan Papua.
Khusus megathrust, kekuatan gempa maksimal yang dapat dilepas mencapai lebih dari M 7,5. Tren 2019 menunjukkan gempa muncul di wilayah sesar aktif dan bersifat merusak. Ancaman lain adalah gempa bumi yang bisa muncul dari sesar aktif yang belum terpetakan atau dikenal dengan blind fault. Kejadian gempa bumi dapat menyebabkan bencana lain, seperti tsunami dan likuefaksi.
Faktor ketiga adalah status kerentanan masyarakat. Kesiapan masyarakat menghadapi bencana diukur melalui kajian kapasitas daerah. Penilaian kapasitas daerah mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana.
Dari semua provinsi di Indonesia, lebih dari separuhnya memiliki kapasitas ”sedang” dalam menghadapi bencana (56 persen). Adapun 41 persen provinsi yang berkategori kapasitas ”tinggi”, hampir separuhnya berada di Pulau Jawa. Peningkatan kapasitas daerah belum merata. Semua provinsi di bagian timur Indonesia masih berstatus sedang, padahal salah satu lokasi bencana yang cukup intensif terjadi di kepulauan Maluku dan sekitarnya. Satu provinsi yang memiliki kapasitas rendah adalah Kalimantan Utara.
BNPB juga menghitung risiko bencana multi-ancaman seluruh Indonesia. Hasilnya, ada 254 juta jiwa yang berisiko tinggi rentan terkena bencana. Jumlah paling tinggi berada di Jawa Barat (46,5 juta jiwa) dan Jawa Timur (38,6 juta jiwa). Potensi kerugian secara fisik karena bencana mencapai angka sangat tinggi, yaitu Rp 670 triliun.
Sementara kerugian ekonomi diperkirakan Rp 481 triliun. Dampak lain yang muncul adalah kerusakan lahan karena bencana yang berpotensi mencapai 80 juta hektar. Kondisi kerentanan masyarakat Indonesia diperparah dengan minimnya pengetahuan akan bencana. Dari sekitar 200 juta penduduk yang tinggal di wilayah rawan bencana, setidaknya 85 persen belum memahami aksi tanggap bencana dan belum pernah mempraktikkannya (Kompas, 16/4/2018).
Indeks resiliensi
Tingkat bahaya, kerawanan, kerentanan, dan risiko bencana merupakan formulasi yang dapat dipakai untuk menyusun resiliensi bencana secara nasional sehingga proses kesiapsiagaan dan mitigasi bencana tidak dijalankan dengan sembarangan. Resiliensi bencana dibangun melalui proses yang berkesinambungan antara kesiapsiagaan dan kerentanan. Setidaknya ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengukur resiliensi sebuah wilayah dan menyajikannya dalam bentuk sebuah indeks.
Secara global, salah satu metode mengukur resiliensi bencana dijelaskan oleh Tom Perfrement dan Tracey Lloyd melalui sebuah hibah riset 2015 Australia-Netherlands Water Challenge yang disajikan di laman Indeks Resiliensi Bencana (Disaster Resilience Index). Indeks Resiliensi Bencana memiliki empat faktor penyusun, yaitu lingkungan sosial, wilayah terbangun, lingkungan alami, dan kondisi ekonomi. Setiap faktor disusun oleh banyak parameter yang semuanya disetarakan menggunakan pembobotan.
Resiliensi di bidang sosial, misalnya, memungkinkan individu dan komunitas untuk beradaptasi dengan keadaan ekstrem serta mengurangi dampaknya melalui interaksi antarindividu ataupun individu dengan komunitas. Faktor sosial disusun oleh persentase usia lanjut usia, akses transportasi, kemampuan berbahasa lokal, dan persentase penyandang disabilitas.
Faktor lain yang berpengaruh terhadap resiliensi bencana suatu wilayah adalah kondisi ekonomi. Salah satu penggerak terbesar dalam pemulihan pascabencana berasal dari perekonomian. Parameter penyusunnya adalah persentase pekerja, tingkat kesenjangan ekonomi wilayah, kepemilikan rumah, dan pendapatan per kapita.
Resiliensi bencana nasional
Di Indonesia, pengembangan resiliensi bencana secara nasional dilakukan oleh Ratih Dyah Kusumawati dan kawan-kawan melalui International Journal of Disaster Risk Reduction yang berjudul ”Developing a Resilience Index Towards Natural Disasters in Indonesia” pada 2014. Penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dan Kota Padang, Sumatera Barat.
Hasil riset menemukan, di kedua wilayah ada kondisi yang tangguh terhadap bencana dengan nilai indeks resiliensi cukup tinggi. Namun, kondisi meminimalkan dampak bencana dan mempersingkat periode pemulihan ini masih perlu mendapat perhatian khusus. Membangun resiliensi yang komprehensif di Indonesia bukan hal mustahil.
Kesadaran akan bencana telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat. Namun, membangun sebuah indeks resiliensi bencana tak bisa sembarangan karena harus mengutamakan poin keberlanjutan. Kemampuan untuk kembali pulih setelah bencana menentukan seberapa lama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung.
Memotong durasi pemulihan pascabencana berdampak pada banyak hal, termasuk intensitas pembiayaan yang ditanggung negara. Selama ini bencana alam menjadi salah satu sumber risiko fiskal bagi perekonomian nasional atau APBN. Kementerian Keuangan mencatat, rata-rata kerugian ekonomi langsung akibat bencana alam pada 2000-2016 mencapai Rp 22,85 triliun per tahun.
Pemerintah pusat belum sepenuhnya mampu menanggung seluruh kerugian akibat bencana. Melihat sistem pembiayaan kebencanaan yang belum stabil dan banyaknya kejadian bencana di Indonesia, perumusan indeks resiliensi bencana menjadi salah satu alternatif metode mengiring proses pemulihan pascabencana agar lebih fokus dan terencana. (LITBANG KOMPAS)