Pembocoran Lokalitas Sastra, Strategi Literer dan Nasionalisme Kita
Sastra bermuatan lokal tak hanya memperkaya khazanah kesusastraan kita, tetapi juga membentang keberagaman dan multikultur sebuah bangsa. Bagi pembaca, lokalitas mendekatkan mereka kepada realitas akar bangsanya.
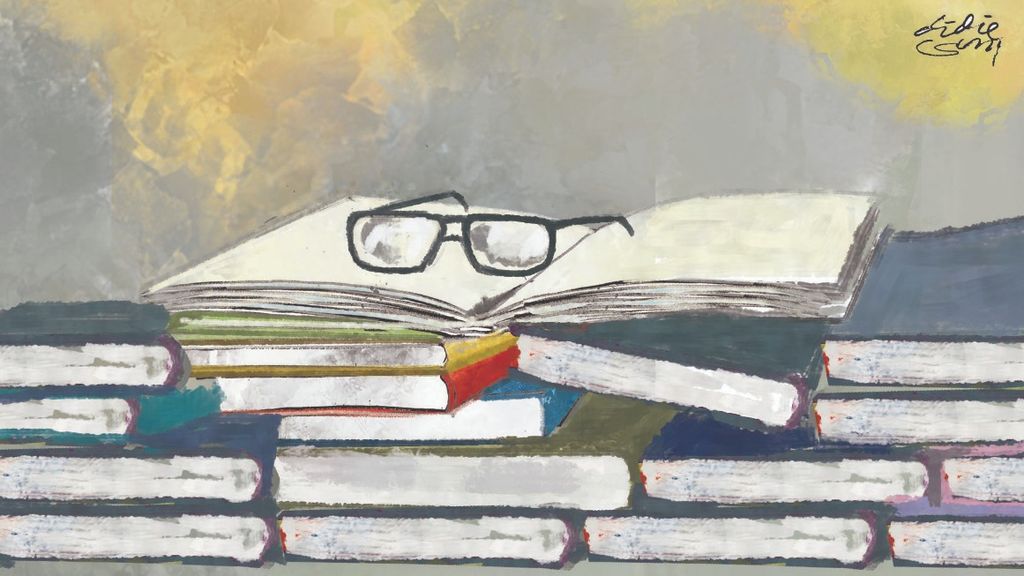
Lokalitas sudah lama mewarnai karya sastra Tanah Air dalam latar kultur berbeda-beda. Sejak era kolonial hingga era mutakhir, karya berwarna lokal lahir dan terus diminati. Roman Balai Pustaka, novel peranakan Tionghoa, hingga puisi dan prosa tahun 1980-an yang dikukuhkan lewat konsepsi ”kembali ke akar, kembali ke sumber” dapat dirujuk perihal ini.
Generasi terkini pun tak meluputkan lokalitas sebagai basis penciptaan. Karya Faisal Odang tentang Toraja, Niduparlas Erlang tentang Mentawai, atau karya Benny Arnas tentang Linggau adalah sedikit contohnya.
Ini bukan saja memperkaya khazanah kesusasteraan kita, juga membentang keberagaman dan multikultur sebuah bangsa. Tentu modal besar dalam membentuk imajinasi kebangsaan yang bermuara kepada konsep nasionalisme. Lewat pembacaan sastra dari dekat, audiens akan lebih mengenal watak/karakter, pikiran dan orientasi masyarakatnya sehingga melahirkan kecintaan dan rasa memiliki satu sama lain.
Sekaligus inilah tantangan dan peluang. Bukan saja bagi pembaca, juga bagi sastrawan sendiri sebagaimana akan kita lihat nanti. Yang jelas, bagi pembaca, lokalitas mendekatkan mereka kepada realitas akar bangsanya. Terbayangkan, dengan membaca sastra berwarna lokal, tak ada lagi di antara kita yang tak bisa sekadar membedakan antara Pulau ”Sumba” dengan ”Sumbawa”, misalnya—sebagaimana dirisaukan seorang travel-writers—bahkan lebih dari itu.
Baca juga: ”Harapan” dalam Karya Sastra
Bukan hanya membedakan nama pulau, juga memahami tradisi di wilayah bersangkutan. Tanpa harus menyebut ”kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah”, apa yang diangkat sastrawan dari rahim kulturnya, memberi kesadaran bahwa kita hidup bukan hanya di atas ribuan pulau, juga di tengah beribu adat, bahasa, ritus, laku, seni, dan kebudayaan.
Dalam konteks ini, bolehlah kita pinjam ungkapan Emha Ainun Nadjib sekitar 40 tahun yang lalu, yakni ”Indonesia bagian dari desa saya”. Jika ”desa” kita asumsikan sebagai daerah atau enclave budaya, maka pergulatan manusia Indonesia tecermin dalam kaca benggala kebudayaan daerah yang ditransformasikan sastra dalam konsep penciptaan lokalitas. Akan tersualah metamorfosis tesis Emha: ”Nasionalitas (Indonesia) bagian dari lokalitas (daerah/kultur) saya”.
Artinya, persoalan-persoalan manusia Indonesia di panggung kebangsaan (nasional) dapat dilacak akar soalnya ke wilayah asal-usul, ke hulu kebudayaan lokal. Di sinilah, jika kita bicara nasionalisme, maka sastra bermuatan/berwarna lokal bakal memberi ruang imajinasi yang luas dan beragam. Dengan demikian, makin kuat nasionalisme menyatakan satu-kesatuan (ingatlah Sumpah Pemuda atau NKRI harga mati), justru makin kukuh kesadaran kita pada keberagaman, keberbagaian. Negara-bangsa boleh tunggal, suku-bangsa dan kebudayaannya mutlak jamak.
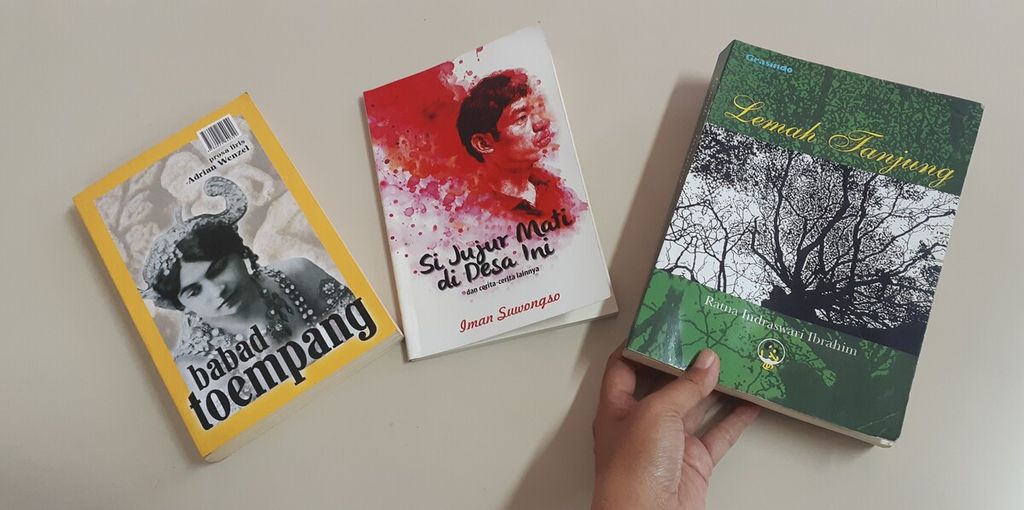
Sejumlah buku sastra yang bermuatan lokal, yaitu tentang Malang, 9 Oktober 2021.
Pembocoran, pengayaan?
Dalam sejumlah karya sastra, lokalitas tampak mengalami pembocoran, yakni masuknya fakta, pikiran, dan peristiwa-peristiwa non-etnik ke tengah-tengah masalah etnik. Tentu diasumsikan lokalitas menjadi tidak ”murni” lagi, dan fokus cerita bisa saja beralih. Masalah puak bukan lagi menjadi pusat cerita, padahal lokalitas diharapkan mengangkat jagad leluhur dari yang selama ini dianggap terpinggirkan—sebagaimana dalam realitas pembangunan ala dunia ketiga—mengalami peminggiran lagi di dunia fiksi, di dunia cerita.
Jika demikian, apakah pembocoran merupakan pengayaan atau justru peminggiran?
Saya tidak bisa menjawabnya secara langsung, tetapi dapat kita lihat bagaimana lokalitas bekerja dengan pembocoran sebagai fakta literer atau bahkan strategi literer. Kita bisa lihat novel Umar Kayam, Para Priyayi (1992), sebagai contoh. Dalam novel ini, kultur Jawa Mataram menjadi warna lokal yang berpusat di kota kecil Wanagalih. Proses menjadi priyayi baru didedah sedemikian rupa. Uniknya, proses itu dilakukan dengan cara menerobos pagar yang mungkin saja sudah digariskan leluhur secara turun-temurun, berdasarkan trah atau silsilah. Namun, Kayam dengan cerdik melihat satu kemungkinan yang tak berhubungan dengan ritus-ritus tradisional. Ia justru menghubungkannya dengan ritus-ritus modernitas melalui pendidikan.
Kayam dengan cerdik melihat satu kemungkinan yang tak berhubungan dengan ritus-ritus tradisional. Ia justru menghubungkannya dengan ritus-ritus modernitas melalui pendidikan.
Dari dunia pendidikan—yang juga memiliki struktur hirarkisnya, apalagi pendidikan kolonial—lahirlah sosok priyayi baru: Lantip. Seorang yang aslinya bernama Wage, tak punya hubungan darah dengan trah Sastrodarsono. Ia anak penjaja kue keliling dari Desa Wanalawas, dijadikan anak angkat Sastrodarsono dan disekolahkan.
Bahkan, Sastrodarsono tidak lain juga anak seorang petani Desa Kedungsimo bernama Mas Atmokasan. Ia menjadi priyayi juga lewat proses pendidikan, diangkat sebagai guru bantu, ditambah pergaulannya dengan Ndoro Seten dan perkawinannya dengan Aisyah, anak Paman Mukaram yang telah lebih dahulu mentas sebagai priyayigung.
Dari sini terlihat bahwa warna lokal novel Kayam yang mula-mula bersifat antropologis, mengalami pergeseran, jika bukan pengayaan, lewat cara sosiologis. Pembocoran antar-disiplin ilmu sosial itu memungkinkan lokalitas mengalami perluasan lebih dari persoalan etnik.
Baca juga: Bukan Sastra Inferior
Namun, para priayi baru terdidik itu tetap hanya berinteraksi dengan budaya Jawa, sekalipun mereka sudah tersebar ke kota-kota besar yang bersifat urban. Tak ada kultur lain masuk untuk membuatnya majemuk. Lalu, dengan cara yang cenderung datar dan tak emosional, Kayam melakukan pembocoran berikutnya. Ia membawa masuk perkara ideologi komunis dan memuncak pada tragedi 65 yang melibatkan salah seorang anak-jati keluarga Sastrodarsono, Harimurti. Sebelumnya, Kayam sudah memasukkan cerita komunis tahun 1948 atau era Muso di sekitaran Madiun, tak jauh dari Wanagalih. Tetapi belum ada tokoh yang terlibat langsung.
Tentu saja soal ideologis itu merupakan lokalitas non-etnik, sebagaimana ia memperkaya jagad priyayi Jawa dengan pendidikan era kolonial. Hal yang melahirkan bukan saja status sosial baru sebagai guru, juga hasrat perlawanan sebagaimana ditunjukkan Mas Martoatmodjo. Ia seorang kepala sekolah yang setia membaca koran berbahasa Indonesia, Medan Priyayi dan koran berbahasa Jawa, Sarotomo. Ini membangkitkan cinta Tanah Air (nasionalisme), sekalipun ia hidup dibayang-bayangi intaian opziener dan polisi kolonial.
Lewat cara ini tindakan dan motif-motif tokoh jadi beragam. Pergaulan lintas-batas, termasuk soal ideologi. Sampai di sini, pembocoran lokalitas memperkaya lokalitas itu sendiri.
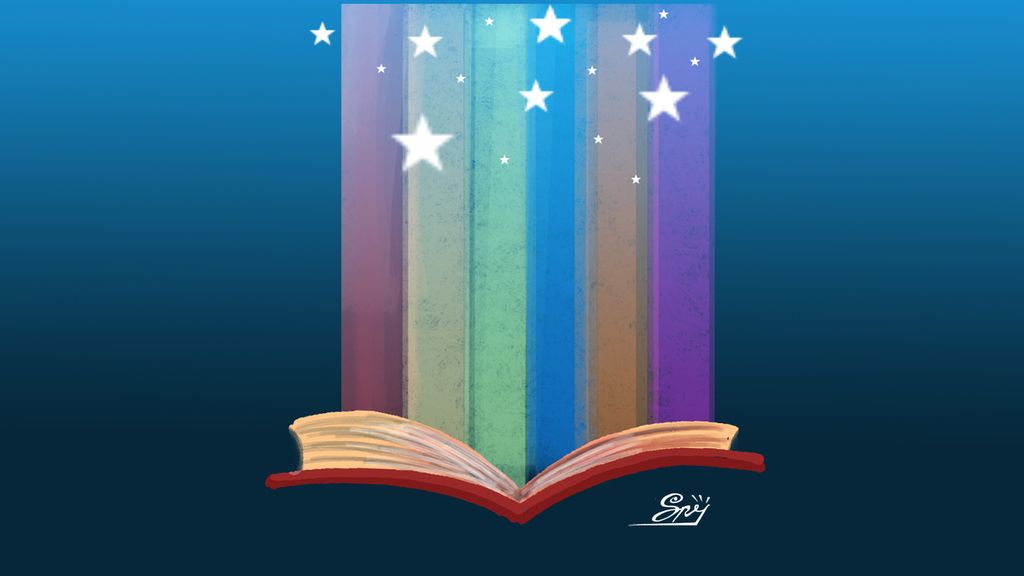
Nasionalisme, pascakolonial
Lihat pula novel Ahmad Tohari, Ronggeng Dukuh Paruk, terasa bernilai historis bukan semata karena mengandalkan lokalitas Jawa Banyumasan ngapak, yang era Mataram jaya disebut negara-manca, melainkan karena masuknya dunia pergolakan politik ke dalam kehidupan Srintil. Dengan demikian, lokalitas mendapat kerangka baru dan plot yang menjangkau ke luar dinding Dukuh Paruk beserta makam keramat Ki Secamanggala itu.
Bahkan, peristiwa keracunan tempe bongkrek bukan sekadar peristiwa biasa. Itu pintu masuk yang menghubungkan dukuh dengan dunia luar. Sebutlah modernitas, yakni datangnya mantri dan tenaga kesehatan untuk memeriksa para korban. Dari situ pula psikologis rindu-dendam Rasus terbentuk, seorang pemuda desa yang telak membayangkan nasib sang emak. Nasib yang tak jelas juntrungnya pasca-emak dibawa tenaga medis untuk diperiksa ke kota.
Dari beberapa korban yang dibawa, hanya sang emak yang tidak kembali pulang. Ini memunculkan kompensasi dan bayang konspirasi di kepala Rasus, bersamaan gencarnya desas-desus. Ada yang bilang emaknya dijadikan kelinci percobaan, tubuhnya dicincang dan jeroannya dibongkar, di laboratorium. Namun, ada pula yang bilang emaknya dapat disembuhkan, lalu pergi bersama kepala mantri. Kemungkinan mereka kawin lari dan emaknya hidup enak di kota. Ini membangkitkan rasa marahnya di sisi lain. Kelak, semua ini mewarnai watak Rasus bukan saja sebagai anak, juga sebagai warga dan tentara.
Bahkan, peristiwa keracunan tempe bongkrek bukan sekadar peristiwa biasa. Itu pintu masuk yang menghubungkan dukuh dengan dunia luar.
Dengan begitu, masuknya dunia modern (pendidikan, kesehatan, ideologi) ke jagat lokalitas Dukuh Paruk dan Wanagalih ataupun Wanalawas bukanlah peristiwa biasa atau ujug-ujug yang sekadar lewat, tetapi berpengaruh signifikan membentuk karakter dan plot, termasuk benturan dan konflik. Artinya, peristiwa sosial-politik dan hal-hal ideologis tersebut bukan rembesan, melainkan pembocoran yang disengaja, sadar dan terpola. Sebuah konsep. Ini memungkinkan novel-novel berwarna lokal bukan saja bertambah kaya, melainkan memiliki aktualitas dan relevansi dengan sejarah zaman.
Sementara novel-novel yang mengandalkan lokalitas etnik an-sich, tanpa membuka pintu kepada kultur dan dispilin lain yang lebih luas, kadang terlokalisasi secara etnosentris. Cerita berhenti di pusat puak suatu komunitas, di mana plot ”menggenang” di wilayah yang terdislokasi. Detail memang, tetapi ia kerap berhenti menjadi pengetahuan etnografis.
Novel Warisan karyaChairul Haruntentang seluk-beluk pusaka Minang, misalnya, menjadi berputar dalam satu perkara yang dibumbui labirin percintaan. Menurut Gus tf Sakai, tak jauh beda dengan novel pop. Chairul tidak melakukan upaya pembocoran dengan displin yang ketat, kecuali pola kehidupan kota besar yang dipraktikkan Rafilus secara longgar dan bebas.
Bandingkan dengan novel Burung Kayu karya Niduparas Erlang. Ada pembocoran melalui tangan negara yang masuk dalam konflik tanah ulayat dan ekologi secara luas. Juga intimidasi atas adat dan kepercayaan. Betapa pun dalam batas tertentu pola Erlang dalam pembocoran ini terkesan streotipe. Tetapi tak tertolak bahwa lokalitas vis to vis negara, memungkinkan Mentawai terangkut dalam isu-isu lingkungan, pluralitas, dan politik secara lebih nyaring dan terbuka.
Baca juga: Lanskap Sejarah Sastra Indonesia
Bagaimana dengan novel Chinua Achebe, Segalanya Berantakan, yang sangat detail mengulik dunia etnografis suku bangsa Ibo di Afrika?
Memang, novel ini detail sejak awal dengan konsep, falsafah, dan ritus hidup mereka, tetapi setahap demi setahap watak anggota puak berkembang seiring kesetiaan pada tradisi. Okonkwo harus ikhlas membunuh anak angkat kesayangannya karena tradisi menginginkannya demikian. Lewat pengenalan etos dan tanggung jawab inilah, detail etnografis akhirnya ”pecah telur” ketika datang bangsa kulit putih. Pembocoran dimulai. Agama baru masuk. Kolonialitas bertindak. Inilah antiklimaks: dunia lama yang dipertahankan bertemu dunia baru yang tak terbayangkan. Segalanya menjadi berantakan.
Okonkwo melawan dan memilih mati dengan menggantung diri. Sebuah pilihan yang lahir dari akumulasi pilihan sulit sebelumnya dalam ritus dan tradisi sukunya. Efek dan risiko pembocoran menjadi logis. Dunia lama terbuka dengan satu celah yang membuat kita masuk bukan lagi dengan rasa asing, tetapi dekat dengan peristiwa historis seperti kolonalisme yang meminta banyak tumbal. Lewat cara ini, nasionalisme negara-negara dunia ketiga dibangkitkan. Kesadaran akan situasi/posisi dirinya sebagai negeri pascakolonial dikibarkan.
Raudal Tanjung Banua, Cerpenis

Raudal Tanjung Banua