Penelitian Sejarah
Pemerintah maupun masyarakat Indonesia seharusnya merespons tidak secara emosional, tetapi dengan kecerdasan, kedewasaan, dan kearifan intelektual dan kultural, bukan dengan prinsip aji mumpung untuk dapat keuntungan.

Tarian Kolosal berupa perang perebutan kembali Ambarawa, Jawa Tengah yang diduduki tentara Sekutu 15 Desember 1945. Perang ini dipimpin Kolonel Sudirman. Banyak pahlawan, prajurit TNI AD dan masyarakat berguguran dalam perstiwa itu. Semangat juang mereka harus diterjemahkan bagi kita sekarang dengan kerja keras mengisi kemerdekaan.
Tanggal 17 Februari 2022, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia atas tindakan kekerasan brutal yang sistematik oleh militer Belanda di Indonesia selama 1945-1949.
Permintaan maaf itu berbasis hasil penelitian berjudul ”Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan, dan Perang di Indonesia, 1945-1950”, yang diluncurkan di Amsterdam.
Hasil penelitian, serta permohonan maaf Perdana Menteri Belanda, tersebut kemudian menimbulkan kontroversi. Muncul beragam perspektif, penafsiran, dan reaksi berbeda di Belanda dan Indonesia.
Artikel opini Bambang Purwanto ”Setelah Permohonan Maaf Belanda” (Kompas, 16 Maret 2022) menambah pengetahuan saya yang bukan sejarawan. Ia menjelaskan implikasi yang harus dipahami, juga memaparkan isu-isu yang masih perlu dikaji serta ”konsekuensi ikutan” hasil studi baik politis, finansial, kultural, maupun keilmuan.
Pengajar Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM itu juga mengingatkan: ”Baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia seharusnya merespons tidak secara emosional, tetapi dengan kecerdasan, kedewasaan, dan kearifan intelektual dan kultural, bukan dengan prinsip aji mumpung untuk dapat keuntungan."
Saya simak keprihatinan Bambang tentang sumber daya manusia kita dan pendanaan penelitian sejarah. Keprihatinan itu dia lanjutkan dengan saran agar ”Negeri kita punya agenda untuk terus mengembangkan sumber daya sejarawan yang bermutu dengan keahlian periode keberadaan Belanda di Indonesia sejak akhir abad ke-16 sampai usahanya kembali berkuasa pada 1945-1949”.
Selama ini, lanjut Bambang, kepedulian dalam arti pendanaan yang berkesinambungan di Indonesia masih kurang, terutama untuk studi lanjut sejarawan Indonesia dalam mengkaji masa kolonial Belanda termasuk era 1945-1949. Ketergantungan kepada pihak asing, khususnya Belanda, sangat besar.
Bambang menegaskan, sudah saatnya Indonesia berinvestasi jika ingin memiliki sejarawan yang mumpuni di bidang sejarah Indonesia zaman kolonial Belanda dan 1945-1949.
Sebuah ”tuntutan” yang tepat, menurut saya.
Eduard Lukman Jl Warga RT 014 RW 003, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510
Nama Jalan di IKN

Jokowi di IKN
Dalam berita di harian Kompas (Minggu, 20/3/2022) berjudul ”Persiapan IKN Butuh Dukungan Publik”, Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Dhony Rahajoe menyebutkan, pembangunan infrastruktur di IKN, seperti jalan, dibiayai oleh pemerintah.
”Nusantara” yang sebelumnya merupakan sebutan bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia, kini juga menjadi nama IKN baru.
Karena bermakna kepulauan, saya usul alih-alih menggunakan nama-nama pahlawan, semua nama jalan di IKN menggunakan nama-nama pulau di Indonesia.
Juga, jalan yang sudah ada diganti dengan nama-nama pulau. Hal ini akan menjadi keunikan dan ciri khas IKN.
Penggunaan nama-nama pulau mencerminkan konseptualisasi wilayah geografi Indonesia berupa pulau-pulau yang disatukan oleh lautan.
Pembakuan nama rupa bumi unsur pulau yang dimulai sejak 2005 mencatat 16.671 pulau sudah dilaporkan ke PBB melalui sidang UNGEGN (United Nation Group of Expert on Geographical Names) tahun 2019.
Pada Gazeter Republik Indonesia tahun 2020, terdata pertambahan pulau menjadi 16.771 pulau. Kemudian, dalam rapat tindak lanjut koordinasi data pulau yang dipimpin Badan Informasi Geospasial pada 23 Agustus 2021 disepakati jumlah pulau di Indonesia menjadi 17.000 buah.
Penambahan pulau akan didaftarkan dalam pertemuan UNGEGN tahun 2022. Ayo, kita gunakan untuk nama jalan di IKN Nusantara.
Johan Candra SasmitaJl Raya Pondok Hijau Permai, Pengasinan, Rawalumbu, Kota Bekasi 17115
Mandalika

Presiden Joko Widodo didampingi Nyonya Iriana meninjau sirkuit internasional Mandalika yang akan digunakan dalam penyelenggaraan MotoGP, Maret mendatang. Peninjauan dilakukan dalam kunjungan kerja, Kamis (13/1/2022).
Senang dan bangga, Lombok mulai dipandang dunia setelah perhelatan MotoGP 2022 di Mandalika. Lombok adalah kampung halaman orangtua, di mana nenek dan seluruh keluarga besar masih tinggal di sana.
Banyak kawasan wisata indah di Lombok, Mandalika salah satunya. Namun, saya berharap keindahan itu tidak akan hilang seiring berjalannya waktu.
Ayah saya tahu persis bagaimana perizinan dan penguasaan tanah itu di Lombok. Saya hanya berharap ada pengetatan perizinan, pengawasan pembangunan agar sesuai dengan amdal, dan teliti dengan riwayat izin-izin tanah tersebut didapatkan.
Saya tidak ingin Mandalika beberapa tahun mendatang dipenuhi bangunan hotel mewah, menutupi keindahan pantai dan sirkuit.
Dibutuhkan orang yang tegas agar tidak mengeluarkan izin dengan semena-mena.
Susanti HJakarta Barat
Sartono Kartodirdjo
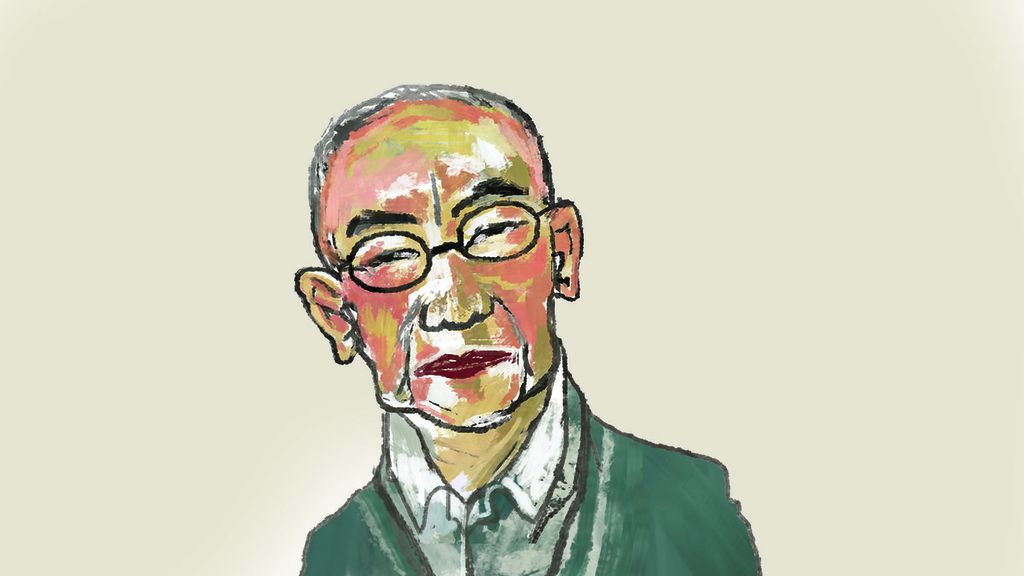
Membaca tulisan St Sularto, ”Sartono Kartodirdjo Sang Asketis Intelektual” (Kompas, 18/3/2022), kami ingin memberikan dua catatan.
Pertama, nama Sartono baru ”sepenuhnya diturunkan” dari barisan editor Sejarah Nasional Indonesia (SNI) pada edisi SNI ke-4 (1984). Nama beliau rupanya masih tercantum dalam SNI Jilid V edisi ke-3 (1982/1983).
Kedua, Sartono secara luas diyakini sebagai peraih PhD pertama dalam bidang sejarah dari luar negeri.
Namun, dari penelitian sejarawan Filipina, Rommel Curaming, terungkap bahwa empat tahun sebelum Sartono meraih doktor dari Universitas Amsterdam, Lie Tek Tjeng telah meraih PhD dari Universitas Harvard tahun 1962 dalam bidang sejarah Jepang. Disertasinya berjudul Mutsu Munemitsu, 1844-1897: Portrait of a Machiavelli.
Temuan Curaming tertuang dalam disertasinya di ANU (2006), dibukukan dengan judul Power and Knowledge in Southeast Asia (2020).
Adalah betul apa yang ditulis Sularto bahwa ”Sartono adalah sejarawan pertama Indonesia yang meraih gelar doktor ilmu sejarah dari luar negeri”. Namun, apabila berbicara wilayah kajian seorang sejarawan secara umum, beliau bukan yang pertama.
Oleh karena S-1 dan S-2- nya dari disiplin sinologi, Lie Tek Tjeng (1931-2009) yang seumur hidupnya bekerja selaku pakar Asia Timur di LIPI itu terlupakan dari pembicaraan sejarawan Indonesia.
Didi Kwartanada Meruya, Jakarta Barat
Cuci Darah
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2018%2F09%2F18%2Fb370a367-20f5-4cc8-bd83-363991882e2f_jpg.jpg)
Sejumlah pasien ditunggui keluarganya saat melakukan cuci darah di instalasi hemodialisis Rumah Sakit Umum Daerah Dr Moewardi, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (7/4/2018). Setiap hari unit instalasi tersebut melayani 76 pasien cuci darah yang sebagian besar merupakan pengguna BPJS. Pasien pengguna BPJS yang rata-rata melakukan cuci darah sebanyak dua kali per minggu dapat menggunakan layanan di instalasi tersebut secara gratis. Bagi pasien yang tidak menggunakan BPJS dikenakan biaya sekitar Rp 900.000 untuk satu kali cuci darah.KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO
Kompas (Jumat, 21/1/2022) menyajikan ulasan tentang dua tokoh pejuang hak pasien cuci darah. Saya baru tahu bahwa ada organisasi ini. Di RS tempat saya cuci darah tidak tersedia informasi ini. Terima kasih Kompas.
Tentunya, saya ingin bisa bergabung dengan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI). Hal yang menarik adalah tujuan organisasi ini. Selain membela hak pasien terkait regulasi pemerintah, kebijakan manajemen RS, perhatian dokter, serta ketersediaan alat dan kelengkapan cuci darah, KPCDI juga menjadi sarana pasien membangun komunitas.
Kebutuhan untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi sangat penting saat pasien bisa menjalani cuci darah bertahun-tahun, bahkan mungkin seumur hidup.
Pasien, di mana pun berada, membutuhkan wadah untuk menopang semangat dan optimisme bertahan, karena banyak hal yang harus mereka jalani dan tempuh.
Sebagai pasien, yang menjadi bagian dari proses terapi hemodialisis di sebuah RS, saya melihat dan mengalami sendiri situasi kebersamaan yang terbina di dalam ruang hemodialisis itu. Hal ini memang diperlukan.
Suasana gembira, penuh senda-gurau, yang ditingkahi suara keluarga yang mendampingi dan kejenakaan perawat yang tidak lelah-lelahnya mengurusi para pasien dan peralatan yang ada, semuanya membangun suasana penuh kehangatan dan persaudaraan yang menyenangkan.
Tegur sapa dan bincang- bincang santai di ruangan, dengan kawan sesama pasien yang bersebelahan, kadang- kadang yang agak berjauhan, bercerita tentang keadaan kesehatan masing-masing dan juga tentang kehidupan masing-masing, menumbuhkan rasa haru dan solidaritas dengan sesama. Juga keinginan untuk saling membantu, terlepas dari kedudukan masing- masing di dalam strata sosial. Tidak ada jarak, tidak ada perbedaan. Begitu pula para ”pendamping”.
Kehadiran ”pendamping”, siapa pun dia, menjadi suatu hal yang penting. Bukan hanya untuk membantu makan, minum, dan sebagainya, melainkan juga untuk mendengarkan keluhan, ungkapan harapan, dan memberi obat kehangatan bahwa kami-kami ini ”masih diperhatikan”.
Apa jadinya apabila hal ini tidak terbentuk? Seperti yang diungkapkan oleh Kompas, kalau tidak ada komunitas, ”kami melamun saat pulang cuci darah, berpikir hari esok seperti apa”. Bukan itu saja, kami pun sewaktu menjalani prosesnya bisa melamun memikirkan nasib di masa depan.
Bisakah kami lepas dari ketergantungan pada hal-hal yang dikemukakan di atas? Bila stres mendera, ada saja hal-hal yang bisa terjadi.
Pendamping, selain sosok sesama pasien, juga merupakan tokoh penting bagi pasien cuci darah. Mereka bisa saja anak yang setia menemani orang tua—bisa lelaki atau perempuan—pasangan hidup yang setia mendampingi, sahabat atau saudara, juga asisten rumah tangga dan tetangga.
Selain kenal, kita pun bisa mengamati dan merasakan siapa yang kurang beruntung dan butuh dukungan karena keluarganya kurang atentif.
Tanpa disadari, kehangatan yang terbina, dan rasa persaudaraan yang terbangun, dapat membantu kami-kami untuk tak kehilangan semangat menjalani terapi. Bahkan sebaliknya, kami bisa tetap optimis walau harus melalui jalan yang panjang berliku dan dalam waktu yang tak menentu.
”Tetap tegar, yakin diri, kita ini sehat! Hanya masih harus cuci darah!” Itu slogan kami.
Alangkah indahnya jika RS, dan para dokter, bersedia jumpa dengan pasien sewaktu- waktu dan menjelaskan kondisi kesehatan serta prospek kesembuhan kami.
Agaknya juga dibutuhkan hipnoterapis yang bisa membantu kami tetap tabah, yakin, dan mampu melakukan self-healing. Semoga.
Zainoel B BiranPsikolog dan Pengamat Sosial.Ciputat Timur, Tangerang Selatan