Ilusi Ilmiah Pancasila
Kehendak pemerintah menguatkan Pancasila secara ilmiah adalah ilusi jika prasyarat ilmiah Pancasila tak dipenuhi, yaitu ketiadaan pemahaman terhadap Pancasila sebagai filsafat dasar negara.

Ilustrasi
Pancasila memang sakti sebagai dasar negara yang final. Akan tetapi, sebagai filsafat dasar negara, Pancasila sangat rapuh. Mengapa? Karena sejak menjadi dasar negara, dimensi filosofis Pancasila tidak pernah dibangun.
Bahkan, ketika pemerintahan Presiden Joko Widodo hendak menguatkan Pancasila secara ilmiah, hal itu menjadi ilusi semata. Kehendak itu tecermin dalam arah kebijakan penguatan Pancasila, ketika pemerintah ingin melakukan pembinaan Pancasila secara ilmiah, salah satunya melalui pendidikan Pancasila.
Hal ini dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan PP tersebut, pemerintah telah mewajibkan kembali pendidikan Pancasila dari usia dini hingga perguruan tinggi.
Baca Juga: Nestapa Pendidikan Pancasila
Kehendak untuk menguatkan Pancasila secara ilmiah juga tecermin dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang No 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) yang menegaskan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan berdasarkan Pancasila. Hal ini juga dinyatakan dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden No 78/2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dalam Perpres BRIN tersebut dinyatakan bahwa fungsi BRIN dalam mengembangkan riset dan inovasi didasarkan kepada Pancasila.
Persoalannya, kehendak menguatkan Pancasila secara ilmiah, baik melalui pendidikan Pancasila maupun riset nasional berdasarkan Pancasila, akan menjadi ilusi karena Pancasila sendiri tidak dibangun secara ilmiah. Dalam hal ini, ilusi diartikan dalam dua hal. Pertama, kehendak yang tidak serius. Kedua, kehendak yang mustahil karena prasyaratnya tidak terpenuhi.
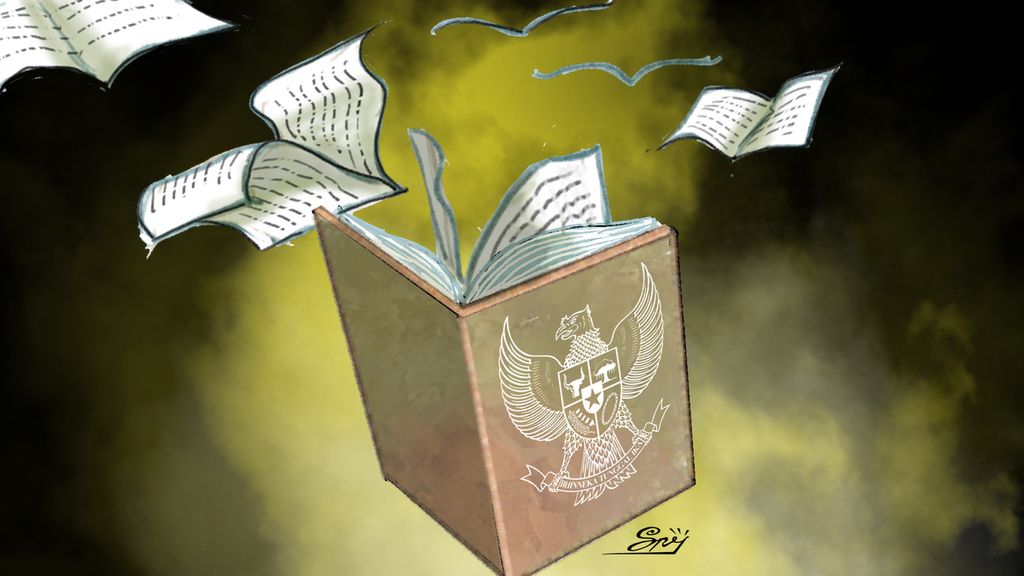
Legalisasi Pancasila
Pertanyaannya, apakah prasyarat ilmiah Pancasila yang tidak terpenuhi itu? Ketiadaan pemahaman terhadap Pancasila sebagai filsafat dasar negara adalah prasyarat yang tak terpenuhi. Selama ini, definisi Pancasila sebagai dasar negara tidak tuntas dipahamkan. Padahal, yang dimaksud dasar negara adalah norma dasar negara (Grundnorm) yang memuat filsafat dasar negara (Philosophische grondslag).
Ketiadaan pemahaman bahwa Pancasila adalah filsafat disebabkan oleh Instruksi Presiden Soeharto No 12/1968 yang membatasi Pancasila sebagai dasar negara hanya dalam teks formalnya di alinea keempat Pembukaan UUD. Melalui Inpres ini, Soeharto telah meniadakan akar historis dan filosofis Pancasila yang terdapat pada kelahiran Pancasila di 1 Juni 1945, serta bentuk kompromi awal Piagam Jakarta. Padahal, TAP MPRS No XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR (Gotong Royong) mengenai Sumber Tertib Hukum di Indonesia menyatakan bahwa Pancasila dasar negara dijiwai oleh Piagam Jakarta dan pidato 1 Juni Soekarno.
Soal penjiwaan Piagam Jakarta atas Pancasila ditegaskan oleh Dekrit Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959. Bagi kelompok Islam yang awalnya menolak Pancasila di tahun 1950-an, konsep Pancasila yang dijiwai Piagam Jakarta mewakili aspirasi Islam. Hasilnya Dekrit Presiden diterima oleh DPR pada 22 Juli 1959 sehingga melahirkan TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tersebut.
Filsafat Pancasila itu mengacu kepada gagasan negara nasional (bukan negara agama) yang humanistik, demokratis, berkeadilan sosial berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sementara itu, status penjiwaan pidato 1 Juni Soekarno atas Pancasila juga merupakan hal fundamental. Mengapa? Karena Pancasila resmi dalam Pembukaan UUD adalah peredaksian formal atas filsafat Pancasila yang dicetuskan Soekarno pada 1 Juni 1945. Filsafat Pancasila itu mengacu kepada gagasan negara nasional (bukan negara agama) yang humanistik, demokratis, berkeadilan sosial berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Meskipun terjadi perubahan posisi sila ketuhanan, dari sila kelima pada rumusan 1 Juni menjadi sila pertama dalam Pancasila resmi, hal tersebut tidak mengubah corak utama filsafat Pancasila. Artinya, dengan naiknya ketuhanan sebagai sila pertama tidak membuat Pancasila menjadi dasar negara teokrasi, tetapi tetap merupakan dasar negara nasional berketuhanan sebagaimana ide Soekarno pada 1 Juni 1945.
Sayangnya, konsep eksistensi Pancasila yang historis itu lalu dipangkas oleh Inpres No 12/1968 tersebut. Sejak itu, kita hanya mengenal Pancasila dalam dimensi legalnya, padahal legalitas itu adalah bentuk yang memuat isi filsafat Pancasila.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F06%2F05%2Fd1b6fc5e-9366-412b-b8fa-895edf3b61a9_jpg.jpg)
Mural bertema Pancasila tergambar di sekitar permukiman warga di kawasan Pinang, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (5/6/2021). Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama yang harus dijaga dan dirawat bersama.
Klaim ilmiah
Pada masa Orde Baru, kita pernah mengalami upaya pengilmiahan Pancasila. Hal ini dilakukan oleh Prof Notonagoro sebagaimana termuat dalam buku Pancasila Secara Ilmiah Populer (1971). Menurut Notonagoro, ia telah berhasil menemukan intisari Pancasila dalam apa yang ia sebut ”Pancasila dalam kondisi obyektifnya”. Kondisi obyektif di dalam Pancasila ini tidak tergantung kepada penafsiran subyektif manusia, termasuk penafsiran dan pemikiran perumus Pancasila.
Upaya Notonagoro dalam menemukan inti Pancasila ini selaras dengan misi Orde Baru untuk memurnikan Pancasila melalui jargon ”Pancasila yang murni dan konsekuen”. Secara yuridis, pemurnian Pancasila telah dilakukan melalui Inpres No 12/1968, juga melalui TAP MPR No V/MPR/1973 serta melalui TAP MPR No II/MPR/1978. Berbagai peraturan yuridis itu membatasi Pancasila hanya dalam Pembukaan UUD. Jika pemerintah Orde Baru meletakkan kemurnian Pancasila dalam Pembukaan UUD, Notonagoro menempatkan kemurnian Pancasila dalam hal-hal obyektif Pancasila.
Pertanyaannya, apakah hal-hal obyektif Pancasila yang merupakan dimensi ilmiah Pancasila? Notonagoro menyebut dua hal. Pertama, manusia, karena manusia adalah subyek yang bersila-sila Pancasila. Kedua, kata-kata dasar dari kalimat sila-sila Pancasila. Kata dasar itu adalah Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil (Notonagoro, 1971: 29-44).
Kalau mengkaji Pancasila, kita mesti berangkat dari asal ide Pancasila, yakni pemikiran Soekarno.
Persoalannya, tepatkah upaya Notonagoro dalam membangun Pancasila ilmiah? Tidak! Mengapa? Terdapat beberapa alasan. Pertama, dalam membangun dimensi obyektif Pancasila, Notonagoro tidak bersifat referensial. Hal ini disebabkan klaimnya bahwa Pancasila yang obyektif adalah Pancasila yang terbebas dari penafsiran subyektif. Padahal, salah satu metodologi ilmiah adalah referensi untuk mendasarkan gagasan pada asal gagasan tersebut. Kalau mengkaji Pancasila, kita mesti berangkat dari asal ide Pancasila, yakni pemikiran Soekarno.
Sayangnya, Notonagoro justru menghapus Soekarno dari filsafat Pancasila. Hal ini dilakukan dengan menggunakan argumentasi yang ia sampaikan pada 19 September 1951 dalam rangka pemberian gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Gadjah Mada kepada Soekarno sebagai pencipta filsafat Pancasila.
Di masa Orde Baru, Notonagoro menggunakan argumentasi pada 1951 tersebut, tetapi untuk kepentingan menghapus peran Soekarno. Hal ini dilakukan dengan menyatakan bahwa Pancasila bukan hasil ciptaan seseorang, melainkan merupakan nilai-nilai yang telah terkandung di bumi Indonesia.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2019%2F03%2F23%2Fc5c216ad-476a-4463-8730-2f857eda5228_jpg.jpg)
Patung Presiden Pertama RI Soekarno, yang dibuat dalam kondisi duduk sambil merenung sila-sila Pancasila di Kota Ende.
Kedua, penempatan kata-kata dasar dari sila-sila sebagai inti-isi-mutlak Pancasila tidak tepat. Misalnya, apa arti kata ”satu” sebagai substansi sila Persatuan Indonesia? Bukankah kata ”satu” masih abstrak dan membutuhkan kata benda untuk menyifatinya, seperti satu kursi atau satu meja? Substansi sila Persatuan Indonesia bukan kata ”satu”, melainkan kebangsaan. Hal ini bisa kita pahami dari pemikiran Soekarno yang dihapus oleh Notonagoro.
Dengan demikian, potensi ilmiah Pancasila telah lama terhapus sejak pembatasan Pancasila hanya dalam dimensi legalnya. Pada saat bersamaan, upaya pengilmiahan Pancasila oleh Notonagoro yang merupakan otoritas utama filsafat Pancasila era Orde Baru juga telah menghapus akar keilmuan Pancasila, melalui konsep Pancasila yang obyektif, ilmiah, dan murni tersebut.
Baca Juga: Menguatkan Nilai-nilai Pancasila
Hingga kini, kelemahan dan dampak negatif dari pemikiran Notonagoro era Orde Baru belum disadari. Hal tersebut disebabkan kajian ilmiah terhadap Pancasila memang belum dilakukan secara serius.
Oleh karena itu, kehendak pemerintah Presiden Jokowi untuk menguatkan Pancasila secara ilmiah adalah ilusi, jika prasyarat ilmiah Pancasila tidak dipenuhi. Termasuk dihidupkannya pendidikan Pancasila akan tetap tidak efektif untuk membuktikan bahwa Pancasila adalah ”sakti” secara ilmiah.
Syaiful Arif, Direktur Pusat Studi Pemikiran Pancasila, CEO Silapedia

Syaiful Arif