Mundur, Kebijakan Pendidikan Nasional
Guru dan dosen memang merupakan jabatan fungsional. Pengaturan jabatan fungsional guru dan dosen PNS yang disamakan dengan ASN pada umumnya jelas suatu kemunduran.
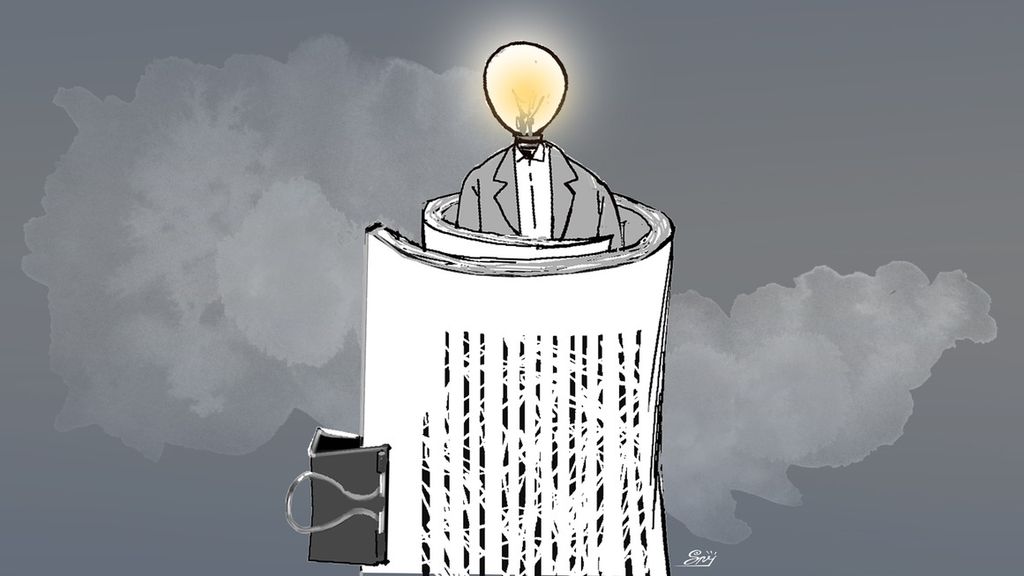
Ilustrasi
Kebijakan pendidikan nasional, terutama terkait dengan relasi negara dengan warganya, semakin lama semakin mundur apabila dibandingkan dengan masa awal kemerdekaan dan Orde Baru. Baik itu terkait dengan otonomi perguruan tinggi negeri (PTN), posisi guru dan dosen, maupun peran warga dalam penyelenggaraan pendidikan. Sikap inklusif yang ditanamkan oleh para pendiri bangsa sudah tidak berbekas lagi. Negara cenderung etatis di dalam penyelenggaraan pendidikan.
Keriuhan para dosen terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN RB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional merupakan salah satu contoh wujud kemunduran kebijakan pendidikan nasional, terutama terkait dengan tenaga guru dan dosen.
Guru sebagai jabatan fungsional juga terkena dampak Permen PAN RB No 1/2023 tersebut. Hanya karena guru tidak membaca regulasinya, mereka diam saja. Sementara para dosen mempelajari permennya dan mampu mengartikulasikan kegelisahannya ke publik. Oleh karena itu, Prof Dr Sulistyowati Irianto, Guru Besar Antrolopologi Hukum UI, melalui opini yang berjudul ”Buruh Dosen” (Kompas, 12/4) sampai pada penilaian bahwa Permen PAN RB No 1/2023 menjadikan dosen sebagai manusia birokrasi tak ubahnya menempatkan dosen sebagai buruh.
Baca juga: Buruh Dosen
Kebijakan pemerintah yang menempatkan profesi guru dan dosen sebagi buruh sudah lama terjadi. Pengelolaan guru pegawai negeri sipil (PNS) seperti aparatur sipil negara (ASN) lain sehingga tidak ubahnya seperti buruh, mulai terjadi sejak otonomi daerah dan pengelolaan guru diserahkan ke pemerintah daerah (pemda).
Masing-masing pemda membuat kebijakan yang sama untuk seluruh ASN. Jika sebelumnya libur guru mengikuti libur murid, sejak otonomi daerah libur guru PNS seperti ASN lainnya, yaitu harus mengajukan cuti pada saat murid-murid libur. Guru juga harus melakukan presensi saat datang dan pulang sekolah. Presensinya juga sudah banyak yang menggunakan finger print. Keberadaan guru di sekolah diatur jamnya sama seperti ASN lain.
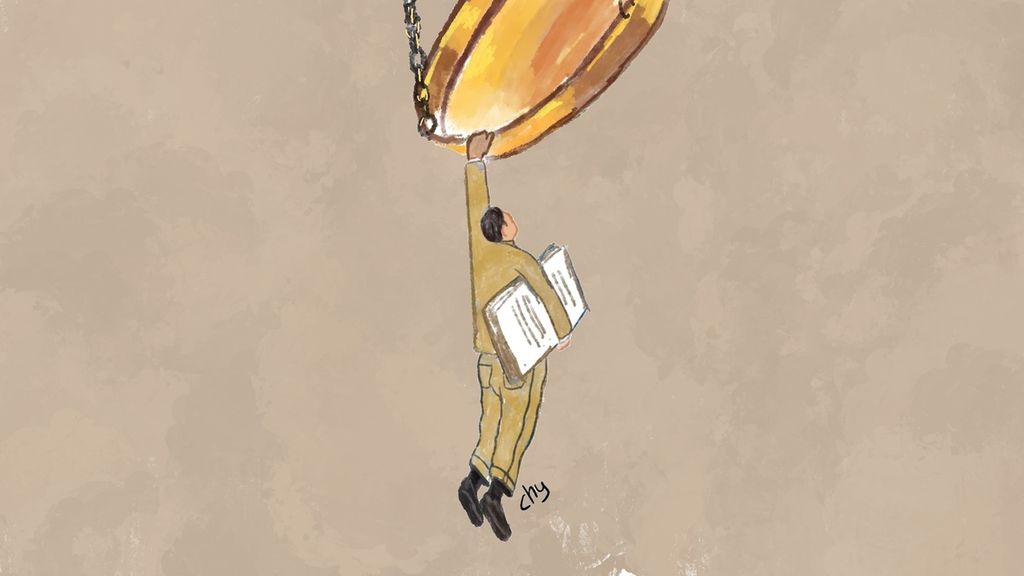
Sementara pengelolaan dosen seperti ASN lain, yaitu harus selalu ada di kampus sesuai jam kerja, presensi finger print atau sekarang ada yang presensi wajah, apabila meninggalkan kampus harus minta izin atasan, kegiatan di luar kampus harus ada surat tugas, dan sebagainya. Itu mulai terjadi setelah adanya perubahan status PTN menjadi BHMN (Badan Hukum Milik Negara), sekarang PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum).
Pola pengelolaan dosen di PTNBH kemudian diadopsi di semua PTN. Secara umum, pengaturan guru dan dosen seperti halnya ASN lain diperkuat oleh UU No 5/2014 tentang ASN yang tidak membedakan jenis dan karakteristik jabatan fungsional.
Guru dan dosen memang merupakan jabatan fungsional, tetapi memiliki karakter yang beda dengan jabatan fungsional lain. Waktu kerja jabatan fungsional lain amat terukur, yaitu 42 jam seminggu. Sementara waktu kerja guru dan dosen tidak terbatas 42 jam seminggu, dan bekerjanya tidak terbatas di sekolah/kampus. Di rumah ketika mengoreksi pekerjaan murid/mahasiswa, membaca literatur agar dapat membuat bahan ajar yang bagus, dan menyiapkan bahan ajar; itu semua adalah kerja-kerja yang harus dijalankan oleh guru dan dosen di luar 42 jam di luar sekolah/kampus.
Sedangkan waktu kerja guru dan dosen tidak terbatas 42 jam seminggu, dan bekerjanya tidak terbatas di sekolah/kampus.
Pengaturan jabatan fungsional guru dan dosen PNS yang disamakan dengan ASN pada umumnya jelas suatu kemunduran karena akan menjadikan guru dan dosen kurang pergaulan (kuper). Padahal, untuk menjadi guru dan dosen yang kaya pengetahuan, kreatif, inovatif, dan profesional; mereka harus rajin mengikuti kegiatan-kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, atau kegiatan sejenis di luar sekolah/kampus.
Sulit mengharapkan guru dan dosen menjadi inspiratif bagi murid/mahasiswa apabila setiap hari dari pagi hingga sore dikerangkeng di sekolah/kampus saja. Birokratisasi guru dan dosen tanpa mengenal kultur akademik itu dapat menjerumuskan bangsa ini ke jurang kehancuran.
Penerimaan dosen di PTN
Contoh lain kemunduran kebijakan pendidikan (tinggi) itu adalah proses penerimaan dosen di PTN. Pada masa lalu, hingga akhir Orde Baru, rekruitmen dosen calon pegawai negeri sipil (CPNS) itu menjadi otonomi kampus. Biasanya fakultas merekrut orang-orang yang dinilai memenuhi kompetensi menjadi dosen, setelah itu diajukan ke rektorat untuk diteruskan ke pemerintah agar dapat diangkat menjadi dosen PNS. Jadi seleksi kualitas calon dosen itu menjadi kewenangan kampus. Setiap fakultas bisa memperoleh calon dosen yang mereka harapkan.
Baca juga: Masih Menarikkah Menjadi Dosen di Indonesia?
Namun, sekarang rekruitmen dosen itu dilakukan secara nasional, dan pemerintahlah yang mendistribusikan ke kampus-kampus. Akibatnya, pihak kampus belum tentu mendapatkan dosen sesuai yang diharapkan karena lulusan PTN dari level yang di bawahnya dapat ditempatkan di PTN yang levelnya lebih tinggi.
Ini merepotkan keduanya. Bagi dosen yang bersangkutan, mereka tergagap-gagap berinteraksi dengan kolega di fakultas yang berasal dari uiversitas tersebut dan memiliki standar kualitas yang lebih tinggi. Sebaliknya bagi PTN yang bersangkutan, mereka merasa rugi karena mendapatkan dosen yang di bawah standar.
Memang ada sisi positifnya sistem rekruitmen dosen seperti itu, yakni latar belakang pendidikan dosen dalam satu PTN menjadi beragam. Namun, sisi negatifnya, kalau dosen yang berasal dari lulusan PTN level lebih rendah lalu ditempatkan di PTN yang levelnya lebih tinggi, bisa berdampak kepada proses penurunan kualitas di PTN yang lebih tinggi tersebut karena standarnya berbeda. Masalah ini sepertinya kurang disadari pemerintah.

Mematikan sekolah swasta
Kebijakan lain yang terasa sekali mundurnya apabila dibandingkan dengan masa-masa awal kemerdekaan hingga akhir Orde Baru adalah secara sistematis mematikan sekolah-sekolah swasta reguler. Wujud kebijakan ini adalah penarikan dan sekaligus penghentian bantuan guru-guru PNS ke sekolah-sekolah swasta atau populer disebut guru DPK (diperbantukan).
Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, tidak ada lagi pemberian bantuan Guru DPK ke sekolah-sekolah swasta. Bahkan, sejumlah daerah menarik guru-guru DPK yang sudah lama bertugas di sekolah-sekolah swasta untuk ditempatkan di sekolah-sekolah negeri. Pasal 2 PP tersebut menyatakan: ”Pengangkatan tenaga honorer menjadi calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan pemerintah ini, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga tertentu pada instansi pemerintah”.
Para perumus regulasi lupa bahwa yang bersekolah di sekolah-sekolah swasta itu juga anak bangsa dan menjadi kewajiban negara untuk mencerdaskannya.
Kehadiran UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN memperkuat PP No 48/2005. Pasal 1 Ketentuan Umum, Ayat (1) menyatakan, ”Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”.
Para perumus regulasi lupa bahwa yang bersekolah di sekolah-sekolah swasta itu juga anak bangsa dan menjadi kewajiban negara untuk mencerdaskannya. Bandingkan dengan kebijakan masa lalu yang jauh lebih inklusif, dengan adanya ”sekolah swasta bersubsidi” dan ”sekolah swasta berbantuan”.
”Sekolah swasta bersubsidi” itu sekolah swasta, tetapi para gurunya berstatus PNS. Sementara ”sekolah swasta berbantuan”, statusnya sekolah swasta, tetapi 50 persen pembiayaannya dari negara, termasuk 50 persen gurunya berstatus PNS.
Keberadaan sekolah swasta bersubsidi dan berbantuan itu sejak awal kemerdekaan hingga akhir Pelita III (1983). Setelah itu dihapuskan dan digantikan dengan kehadiran Guru DPK serta bantuan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk sekolah swasta.
Namun, setelah keluarnya PP No 48/2005 dan UU No 5/2014 bantuan untuk guru DPK itu tidak ada lagi. Bantuan untuk sekolah swasta hanya berupa BOS (Biaya Operasional Sekolah) yang besarannya tergantung jumlah murid yang dimiliki. Padahal, bantuan guru DPK itu amat diperlukan bagi sekolah-sekolah swasta kecil.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F11%2F23%2Fdc639ea3-92b4-453b-a2bb-cb8454d65559_jpg.jpg)
Seorang guru sedang mengajar di salah satu kelas di SD Negeri 192 Kecamatan Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (21/11/2022). Akibat kekurangan guru, banyak tenaga pengajar yang harus mengajar lebih dari waktunya atau di luar latar belakang keilmuannya.
Para perumus kedua regulasi itu tidak memahami aspek historis sekolah-sekolah swasta di Indonesia. Ada tiga tipe sekolah swasta di Indonesia berdasarkan aspek historisnya. Pertama, sekolah swasta generasi I, yaitu sekolah swasta yang lahir sebelum kemerdekaan (misi, zending, Muhammadiyah, Tamansiswa, NU, sekolah-sekolah Thionghoa, dan sebagainya).
Sekolah-sekolah tersebut turut melahirkan para pejuang dan juga generasi yang mengisi awal-awal kemerdekaan. Sampai sekarang keberadaan sekolah-sekolah tersebut masih eksis, meski beragam kualitasnya.
Kedua, sekolah swasta generasi II, yaitu sekolah-sekolah swasta yang lahir pada periode 1945-1990-an. Mereka lahir untuk mengisi kekosongan (pendidikan) yang belum diisi pemerintah karena keterbatasan anggaran. Sebagai contoh, SMP swasta tempat keluarga kami bersekolah. SMP swasta yang berdiri pada 1957 itu adalah satu-satunya SMP di kecamatan kami hingga pertengahan 1970-an.
Baca juga: Guru Digeser, Sekolah Swasta Harus Tetap Spektakuler
Pada 1964, pemerintah mendirikan sekolah tingkat SLTP, tetapi itu SMEP (sekolah menengah ekonomi pertama). Lulusannya dapat melanjutkan ke SMEA (sekolah menengah ekonomi atas). Otomatis mereka yang akan masuk ke SPG, STM, SMA, dan lain-lain masuk ke SMP swasta tersebut. Baru pada 1976 SMEP berubah menjadi SMPN.
Keberadaan SMP swasta tersebut masih eksis sampai 2019 (Akreditasi A). Namun, sekarang hampir sekarat karena tidak memiliki guru DPK dan terkena dampak penerimaan murid dengan sistem zonasi. Dilihat dari peran historisnya, sekolah ini layak dibantu pemerintah.

Didie SW
Ketiga, sekolah swasta generasi III, yaitu sekolah-sekolah swasta yang didirikan berbasis kapital. Pendirinya adalah konglomerat yang memiliki dana besar, dan sangat mungkin pendiriannya itu merupakan bagian dari proses akomulasi kapital melalui sektor pendidikan.
Sekolah-sekolah tersebut umumnya menghindari intervensi pemerintah, termasuk dalam pendanaan karena intervensi pemerintah membuat mereka menjadi tidak nyaman. Sayangnya, cara pandang pemerintah sepertinya melihat sekolah swasta itu dari perspektif sekolah swasta generasi III saja, tidak melihat sekolah swasta dari perspektif generasi I dan II.
Para pengelola sekolah swasta generasi I dan II sekarang juga gelisah karena kebijakan pendirian sekolah negeri yang menjamur mematikan keberadaan sekolah-sekolah swasta yang telah lama berperan mencerdaskan masyarakat.
Baca juga: Menyoal Dunia Pendidikan Kita
Dibutuhkan kearifan para pengambil kebijakan agar kebijakan pendidikan nasional tidak makin mundur. Pertama, PP No 48/2005 sebaiknya dicabut dan revisi UU No 5/2014 tentang ASN khususnya Pasal 1 Ayat (1) perlu dirumuskan kembali agar tetap memberikan perhatian kepada sekolah-sekolah swasta generasi I dan II mendapatkan bantuan guru DPK. Ingat, bahwa yang bersekolah di sana itu juga anak bangsa, dan orangtua mereka tentu juga membayar pajak. Jadi tidak boleh didiskriminasikan.
Kedua, revisi Permen PAN RB No 1/2023 agar membedakan karakteristik jabatan fungsional guru dan dosen dengan jabatan fungsional lain karena dalam praktiknya memang beda. Ketiga, kembalikan otonomi PTN seperti sebelumnya. Perubahan status PTN menjadi PTNBH tidak menjamin otonomi PTN kalau tidak disertai dengan kemauan politik yang kuat dari pemerintah untuk memberikan otonomi kepada perguruan tinggi.
Ki Darmaningtyas, Anggota Penasihat Persatuan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBTS)

Ki Darmaningtyas