Biomassa: Energi Inklusif dan Sirkular
Krisis suplai energi memberikan urgensi lebih tinggi agar Indonesia bertransisi kepada suplai energi terbarukan. Namun, yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana menciptakan transisi energi yang adil dan inklusif?
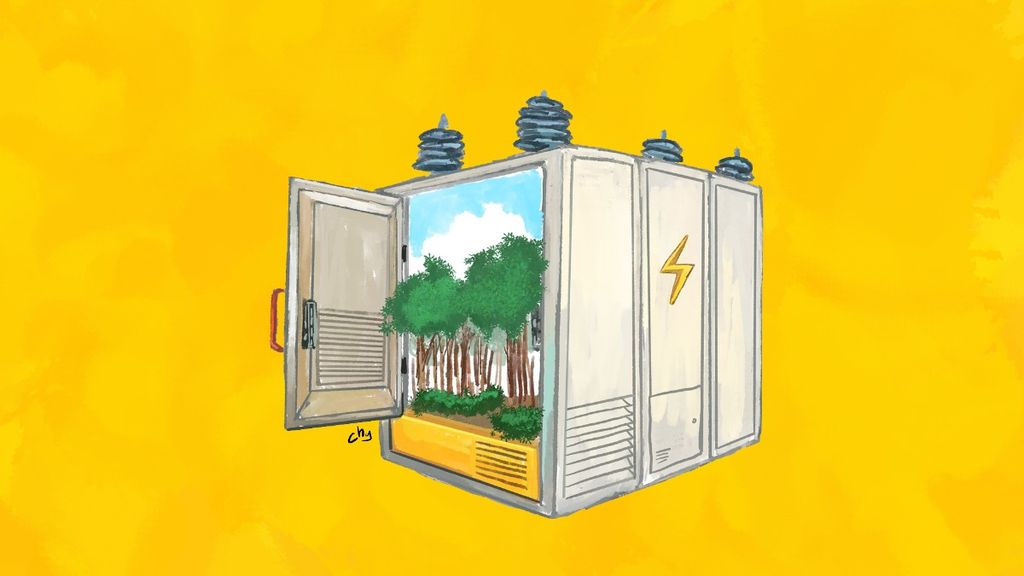
Krisis suplai energi merupakan risiko utama dalam lanskap ekonomi dunia. Tiga risiko utama berikutnya juga berkaitan dengan krisis suplai energi, yaitu krisis biaya hidup, kenaikan inflasi, dan krisis suplai pangan.
Bulan Januari lalu, para pemimpin dunia berkumpul di Davos, Swiss, dalam World Economic Forum 2023 untuk mendiskusikan berbagai macam isu di dunia. Dalam Global Risks Report 2023 yang dipublikasikan pada kesempatan tersebut, para ahli di dunia sepakat tentang hal di atas.
Hal yang sama terefleksikan di Indonesia. Ketika harga bahan bakar minyak meningkat pada September 2022, inflasi bulan tersebut juga meningkat 1,17 persen atau mencapai level tertinggi sejak Desember 2014. Krisis suplai energi sudah sepatutnya memberikan urgensi lebih tinggi agar Indonesia bertransisi kepada suplai energi yang terbarukan.
Indonesia mungkin sudah memiliki fondasi kuat untuk beralih ke energi terbarukan. Komitmen pembiayaan yang diperoleh dari JETP (Just Energy Transition Partnership) menjadi landasan pacu untuk dapat beralih ke sumber energi yang terbarukan. Namun, yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana menciptakan transisi energi yang adil dan inklusif?
Prinsip keadilan dan inklusivitas seharusnya tak hanya dirasakan saat menuai hasil dari transisi energi. Dalam proses transisi, kebutuhan dan apa yang menjadi perhatian dari pemangku kepentingan juga harus diperhatikan, termasuk masyarakat marginal sebagai salah satu pemangku kepentingan.
Dalam hal ini, kita perlu memastikan bahwa transisi energi tak mengindahkan trilema energi: keamanan energi (energy security), keadilan energi (energy equity), dan keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability). Keamanan energi berbicara bagaimana kita dapat selalu memenuhi permintaan energi dengan pasokan energi yang ada. Keadilan energi adalah untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki aksesibilitas terhadap energi, dengan biaya terjangkau.
Baca juga: Kendala Investasi Energi Terbarukan
Adapun keberlanjutan lingkungan merupakan penegasan bahwa penggunaan energi dapat dilakukan secara berkelanjutan, memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, agar manfaatnya masih bisa dirasakan generasi mendatang. Dalam hal ini, biomassa dapat memainkan peran penting mengatasi trilema energi.
Biomassa sebagai energi yang inklusif
Saat ini, sekitar 4.000 desa di Indonesia belum teraliri listrik. Mayoritas berada di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) yang aksesnya sulit terjangkau, bahkan terisolasi.
Salah satu peran utama pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm) dalam memastikan transisi energi yang adil dan inklusif adalah kemampuannya untuk dapat digunakan di mana saja sebagai pembangkit pemikul beban dasar (base load). Hal ini juga berlaku bagi daerah 3T atau bagi daerah yang pasokan listriknya masih belum stabil.
Faktor utama yang harus diperhatikan dari penyediaan listrik melalui PLTBm adalah ketersediaan pasokan bahan bakar. Melalui penerapan prinsip inklusivitas, tantangan ini dapat diubah menjadi sebuah kesempatan untuk memberdayakan masyarakat lokal sebagai pemasok bahan bakar biomassa.
Dengan bahan bakar lokal, kita bisa menciptakan pekerjaan dan peluang ekonomi di daerah perdesaan, serta mengurangi jejak karbon dengan menghilangkan kebutuhan untuk transportasi bahan bakar.
Manfaat lain dari penggunaan PLTBm adalah dapat menghasilkan harga pembangkitan listrik yang lebih murah bagi daerah tersebut, yang disebabkan dua aspek. Pertama adalah sifat base load dari PLTBm yang cocok untuk diterapkan pada sistem off-grid karena tidak membutuhkan tambahan baterai untuk menjamin ketersediaan listrik.
Baca juga: Perguruan Tinggi Digandeng Siapkan Transisi Energi Ramah Lingkungan

Sementara yang kedua adalah pasokan bahan bakar yang berasal dari lokal menyebabkan harga pembangkitan listrik yang lebih murah karena tidak terkendala oleh biaya logistik yang tinggi akibat keterbatasan dan kesulitan akses.
Peran inklusivitas dari biomassa juga dapat dirasakan oleh masyarakat dalam menyediakan pasokan bahan bakar untuk cofiring atau substitusi parsial batubara pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Saat ini, penerapan cofiring biomassa dalam PLTU baru berkisar 1-5 persen dari total bahan bakar batubara dan proporsinya akan terus ditingkatkan hingga 10-20 persen dari total bahan bakar.
Jumlah biomassa yang dibutuhkan untuk substitusi 1 persen batubara adalah sekitar 6 juta ton per tahun. Jika kita memenuhi kebutuhan biomassa ini melalui hutan tanaman, dengan estimasi produktivitas sebesar 30 ton per hektar per tahun, diperlukan lahan seluas 200.000 hektar.
Untuk memenuhi target cofiring sebesar 20 persen, artinya harus tersedia 4 juta hektar lahan hutan tanaman. Pertanyaan besar selanjutnya adalah bagaimana mencukupi kebutuhan lahan tersebut?
Jumlah biomassa yang dibutuhkan untuk substitusi satu persen batubara adalah sekitar 6 juta ton per tahun.
Biomassa sebagai energi yang sirkular
Berdasarkan beberapa penelitian spasial di Indonesia, saat ini terdapat lebih dari 20 juta hektar lahan terdegradasi. Produktivitas lahan yang telah menurun membuat utilisasi dari lahan menjadi minim.
Jika dibiarkan begitu saja, tentunya ini akan mengancam kondisi kemandirian pangan dalam negeri. Terlebih, pada 2045 diperkirakan penduduk Indonesia mencapai hampir 320 juta jiwa, yang artinya kita perlu menambah lahan pertanian untuk mengakomodasi tambahan 50 juta penduduk.
Penyediaan lahan hutan tanaman untuk energi hendaknya tak berkompetisi dengan lahan untuk pangan. Lahan untuk hutan tanaman dapat memanfaatkan lahan terdegradasi yang bukan merupakan kawasan lindung. Luas lahan potensial tersebut diestimasi mencapai 5,8 juta hektar, yang tersebar di seluruh Indonesia.
Indonesia merupakan negara yang kaya akan biodiversitas. Banyak jenis tanaman berkayu dengan rotasi cepat yang cocok digunakan sebagai sumber biomassa, seperti bambu, kaliandra, lamtoro, dan gamal. Tanaman itu juga memiliki manfaat lain, terutama untuk merehabilitasi lahan. Hal ini karena akarnya yang bersimbiosis dengan bakteri pengikat nitrogen bebas dari udara sehingga dapat menyuburkan tanah.
Oleh karena itu, penerapan konsep agroforestri, di mana budidaya tanaman menggunakan sistem polikultur antara tanaman pangan dan tanaman energi, bisa meningkatkan tak hanya ketahanan energi, tetapi juga ketahanan pangan Indonesia. Contoh, sistem budidaya tanaman gamal yang ditanam di samping jagung atau sorgum bisa menyuburkan tanah sekaligus menjadikannya sumber biomassa untuk energi.
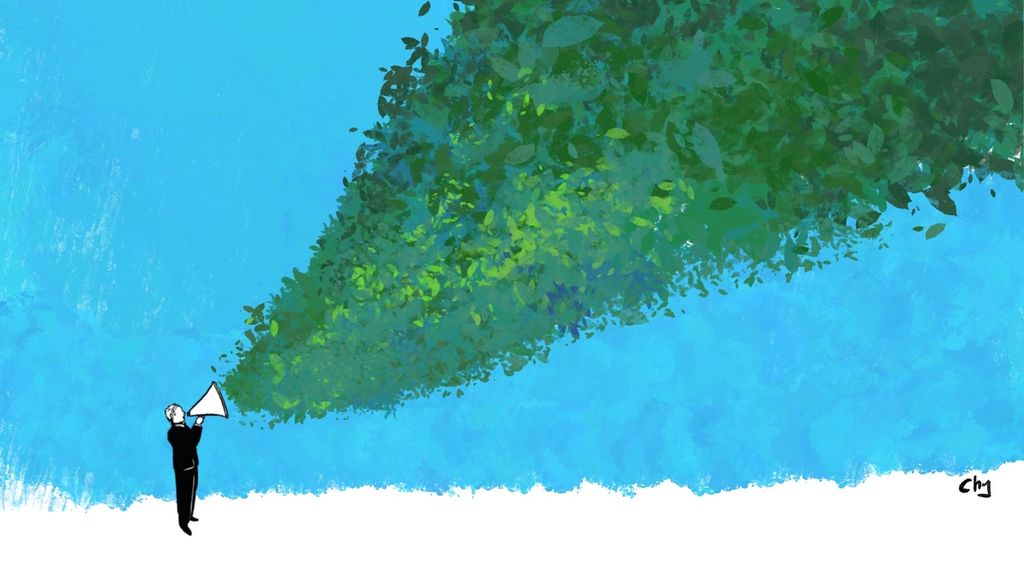
Dengan menerapkan agroforestri, terdapat peningkatan potensi sekuestrasi karbon dari atmosfer yang dapat mencapai 30 ton CO2/ha/tahun. Artinya, jika hutan tanaman diharapkan memasok 20 persen dari kebutuhan biomassa untuk cofiring PLTU, potensi sekuestrasi karbon per tahunnya 120 juta ton CO2, atau setara emisi sektor pertanian di Indonesia.
Terlebih lagi, jika pembangkitnya dilengkapi dengan teknologi carbon capture and storage (CCS), maka akan membuat sistem ketenagalistrikan yang negatif karbon.
Sumber pasokan biomassa juga bisa berasal dari limbah hasil pertanian atau perkebunan. Contoh, limbah perkebunan kelapa sawit, baik berupa tandan kosong yang dapat dijadikan bahan bakar cofiring PLTU, atau dari limbah cair pengolahan kelapa sawit (palm oil milling effluent/POME) yang bisa dimanfaatkan sebagai biogas. Pemanfaatan limbah ini juga kian mendorong peran biomassa sebagai energi yang sirkular.
Penggunaan biomassa untuk pembangkit listrik sebenarnya bukan hal baru. Sebagai contoh, PLTBm Siantan telah beroperasi sejak 2018, dengan bahan bakar berasal dari limbah pertanian dan perkebunan, seperti cangkang kelapa sawit, serbuk kayu, dan sekam padi. Sisa abu pembakaran PLTBm pun dimanfaatkan kembali menjadi pupuk dan menambah sirkularitas.
Penggunaan biomassa untuk pembangkit listrik sebenarnya bukan hal baru.
Tantangan dan kesempatan
Transisi energi dengan bahan bakar biomassa bukanlah tanpa tantangan. Jika tidak direncanakan dan dikelola dengan baik, percepatan PLTBm justru dapat menghambat terpenuhinya transisi yang adil dan inklusif. Tantangan pertama yang perlu diperhatikan adalah alih guna lahan untuk hutan tanaman.
Seperti dijelaskan sebelumnya, lahan ideal untuk hutan tanaman adalah lahan yang terdegradasi atau dengan konsep agroforestri bersama dengan tanaman pangan. Peningkatan permintaan bahan bakar biomassa jangan sampai justru mengurangi tutupan hutan primer Indonesia.
Tantangan berikutnya adalah ketersediaan pasokan biomassa. Untuk mendukung terwujudnya transisi energi yang adil dan inklusif, sumber pasokan biomassa sebaiknya dihasilkan dari daerah sekitar. Jenis tanaman yang digunakan, termasuk dengan teknologi PLTBm-nya, haruslah disesuaikan dengan kondisi geografis daerah sekitar.
Selain itu, stabilitas dari pasokan biomassa perlu diperhitungkan dari awal untuk menjamin ketersediaan pasokan, dengan memperhitungkan kondisi cuaca dan iklim. Untuk lebih menjamin ketersediaan pasokan, pengelola PLTBm sebagai off-taker dari hutan tanaman hendaknya dapat bekerja sama langsung dengan korporasi petani lokal. Korporasi petani dapat berupa koperasi ataupun kelompok usaha tani lainnya.
Melalui korporasi petani, harapannya para petani dapat berkolaborasi secara kelompok demi mewujudkan kesuksesan bersama dan meminimalkan risiko dengan prinsip tanggung renteng.

Terlepas dari tantangan tersebut, pengembangan biomassa sebagai sumber energi juga membawa banyak kesempatan. Perpres No 112/ 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik memberikan keunggulan bagi PLTBm dari segi harga. Harga maksimum (ceiling price) pembelian listrik dari PLTBm adalah yang tertinggi dibandingkan sumber energi terbarukan lain.
Sejauh ini kita baru berbicara dari sektor pembangkitan listrik. Biomassa sebagai energi juga memegang peranan penting dalam transisi energi di sektor transportasi dan logistik. Densitas energi yang tinggi dari biomassa, dalam hal ini biofuel, membuatnya jadi pilihan utama dekarbonisasi sektor ini.
Inisiatif awal telah dimulai sejak lama oleh pemerintah dengan penerapan B30 (biodiesel 30 persen, solar 70 persen). Namun, potensi ke depan masih terbuka sangat luas. Mulai dari peningkatan porsi campuran dari biodiesel sampai penerapan pada moda transportasi udara dan laut. Moda transportasi udara sudah mulai meneliti tentang kelayakan sustainability aviation fuel (SAF) yang berasal dari tumbuhan.
Indonesia sebagai negara tropis sudah memiliki keunggulan kompetitif dalam mengembangkan biomassa, sebuah sumber daya berharga yang dapat memainkan peran penting dalam memastikan transisi energi yang adil dan inklusif. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu mempertimbangkan potensi biomassa dalam rencana transisi energi, sembari tetap memastikan pemanfaatan biomassa dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Bambang PS Brodjonegoro, Guru Besar Universitas Indonesia

Bambang PS Brodjonegoro