Membangun Politik yang Sehat
Politik di negeri ini perlu dikembalikan kepada hakikatnya sebagai jalan menuju kebaikan bersama. Mobilisasi massa dan argumen yang bercorak ”hominen” harus diakhiri.
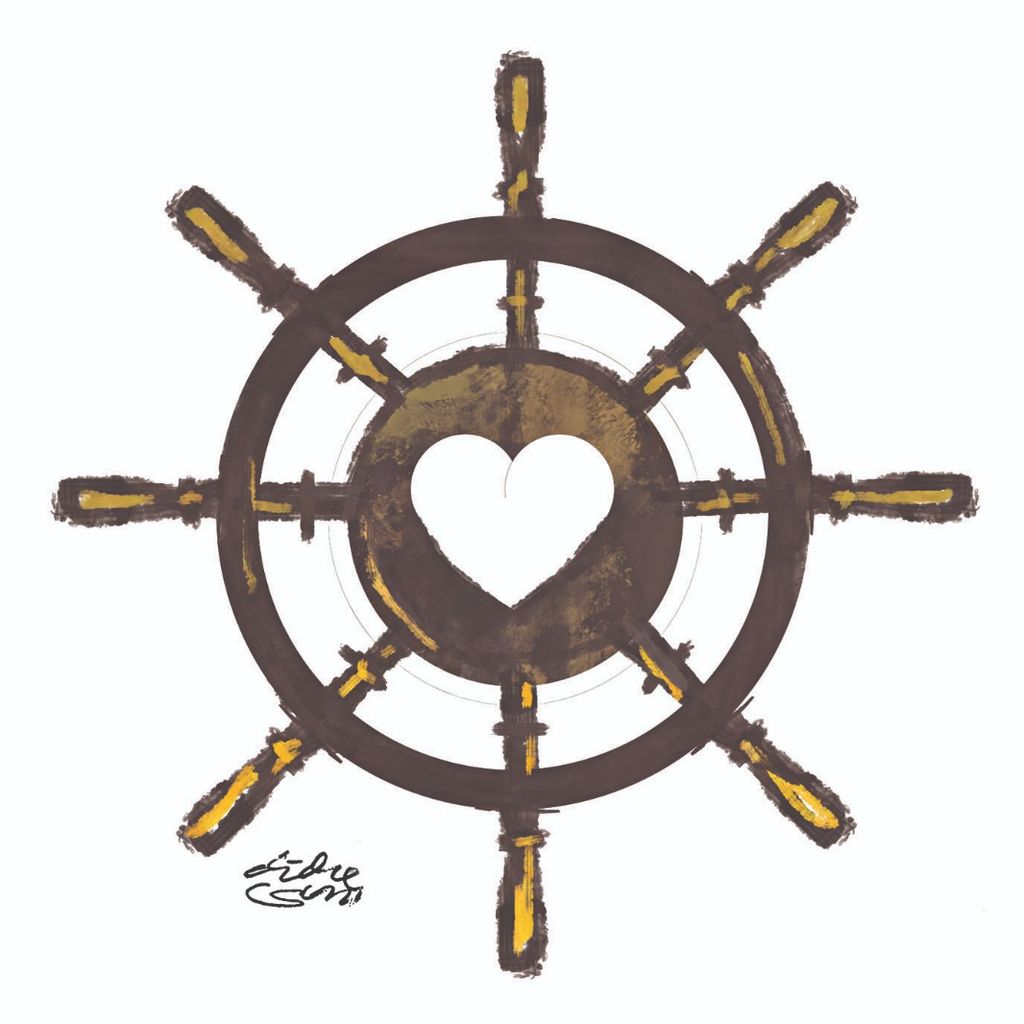
.
Politik bukan sesuatu yang baru. Yunani Kuno menjadi tempat lahirnya kesadaran berpolitik. Politik lahir ketika kesadaran berwarganegara juga mulai tumbuh. Pendek kata politik adalah seni menata kota (polis)–negara kota.
Penggunaan kata polis bukan saja menunjuk negara dalam pengertian secara struktural atau organisasi, melainkan juga menunjuk kepada rakyat yang hidup dalam polis tersebut. Dengan kata lain, pembahasan mengenai polis tidak dapat dilepaskan dari manusia (warga) sebagai entitas dalam bernegara. Karena itu, dalam proses menata kota harus dimulai dengan menata manusia.
Bagi Plato, berpolitik itu sederhana. Jika mampu mewujudkan kesejahteraan warga, polis akan sejahtera. Demikian sebaliknya, jika perilaku warga (manusia) buruk, buruk pula negara: dalam berpolitik manusia harus diletakkan sebagai subyek dan bukan obyek ataupun sarana memperoleh kekuasaan.
Baca juga: Imajinasi Negara atas Rakyatnya
Sederhananya politik lahir sebagai manifestasi kesadaran berwarga negara. Esensi politik adalah usaha untuk menciptakan suatu masyarakat yang sejahtera (well being) demi bonum commune. Politik bukan mobilisasi massa, korupsi, manipulasi, dominasi, dan lain sebagainya. Politik adalah mengundang partisipasi warga dalam mengelola bangsa.
Lebih jauh Aristoletes dalam bukunya, Nicomachean Ethics, mendaraskan bahwa politik inheren dalam etika. Artinya bahwa politik dan etika bukan sekadar sintesis (penggabungan dua variabel), melainkan bersifat tautologis (menyatu) tanpa bisa dipisahkan.
Sejalan dengan hal itu, pemikir modern seperti Hannah Arendt pun sepenuhnya menyadari bahwa politik itu tidak lain adalah dedikasi yang diorientasikan bagi kepentingan orang banyak. Dengan begitu, menjadi seorang politikus harus memiliki spirit melayani.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2018%2F03%2F15%2Ff69bac17-91c8-423d-8c54-23baffe7cb96_jpg.jpg)
Reduksi politik
Seiring perkembangan waktu, politik mengalami reduksi makna. Politik dipersepsi sebagai sarana mengejar kekuasaan semata. Tidak heran apabila dalam benak sebagian masyarakat, politik itu penuh intrik, penuh siasat jahat dan sarat pertarungan kekuasaan.
Pandangan tersebut tentu didasari kepada realitas politik di negeri ini yang demi syahwat politik kita saling berprasangka, melukai, dan meniadakan. Di negeri kita sendiri, politik ala Machiavellian sebenarnya mulai tumbuh seiiring dengan hadirnya rezim Orde Baru. Segala cara dihalalkan demi sebuah kekuasaan dan kultus dari masyarakat.
Sekalipun rezim Orde Baru bemain dengan sangat cerdik dan cantik, ada manipulasi tanpa melalui mekanisme kekerasan. Sekalipun ada skenario kekerasan, sudah diatur siapa yang akan menjadi kambing hitam.
Seiring perkembangan waktu, politik mengalami reduksi makna. Politik dipersepsi sebagai sarana mengejar kekuasaan semata.
Reformasi yang diharapkan mampu melahirkan demokrasi yang sehat justru menjadi antiklimaks. Politisi berlomba-lomba merebut kekuasaan dengan segala macam cara, termasuk isu SARA (politik identitas). Isu SARA atau politik identitas menjadi senjata ampuh bagi para politisi melenggang menuju panggung kekuasaan.
Benarlah apa yang dikatakan oleh Armada Riyanto dalam bukunya, Berfilsafat Politik (2011: 15), bahwa politik di Indonesia terjebak dalam ruang vitual. Dalam ruang virtual, prinsip-prinsip etis tidak lagi memegang peranan penting. Akibatnya, wajah politik di negeri kita dipenuhi para demagogeu, andai mereka baik pun, itu semua tidak lebih dari kamuflase politik.
Baca juga: ”Demokrasi Pemirsa”: Membaca Tontonan Politik Menjelang 2024
Salah satu contoh problem yang cukup menggerus energi adalah konflik identitas yang justru di era reformasi ini mendapat angin segar. Perbedaan tidak lagi dirayakan sebagai kekayaan, tetapi dianggap sebagai ancaman.
Perbedaan adalah sebuah keniscayaan, tanpa perbedaan, maka dunia adalah kehampaan. Di sisi lain, memang perbedaan dapat menimbulkan gesekan, perbatahan, bahkan peperangan. Namun, pada hakikatnya perbedaan mendesak kita untuk menemukan makna kedamaian yang sesungguhnya. Warna-warni yang dimiliki bangsa kita sudah ada sejak zaman dahulu. Meniadakan perbedaan sama saja dengan menganggap Indonesia itu ”tidak ada”.

Selain politik identitas, problem yang juga menarik perhatian publik adalah keadilan. Kata ”keadilan” mudah diucapkan, sulit diwujudkan. Keadilan hanya berpihak kepada mereka yang ”kuat”. Ya, keadilan telah dibajak.
Bagi mereka yang buta hukum, ”keadilan” hanyalah sebuah retorika belaka dan ide yang sangat utopis. Kita sering melihat bagaimana lembaga peradilan hanya menawarkan selebrasi dan drama. Seolah-olah di sana keadilan terwujud, tetapi pada akhirnya kebenaran babak belur oleh preman peradilan.
Karakteristik politik
Ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama. Pertama, dalam politik tidak ada kepastian karena logika politik tidak sama dengan logika Aristotelian di mana kesahihan sebuah premis menghasilkan kesimpulan yang valid. Ini terjadi karena prinsip berpikir logika Aristotelian bersifat deduktif sligositik.
Politik tidak mengandaikan hal tersebut, mengapa? Karena politik adalah seni kemungkinan: yang menjadi aspek pertimbangan bukan derajat kepastian melainkan derajat probabilitas. Itu sebabnya logika yang berlaku dalam ilmu politik adalah logika probabilitas. Hari ini berlaku A, selang beberapa kemudian bisa berubah menjadi A, C, atau yang lain. Tidak ada kepastian dalam politik. Satu-satunya kepastian adalah ketidapastian itu sendiri. Dengan kata lain politik adalah suatu anomali dari keniscayaan.
Politik adalah seni kemungkinan: yang menjadi aspek pertimbangan bukan derajat kepastian, melainkan derajat probabilitas.
Kedua, politik adalah sebuah gagasan dan gagasan itu menjadi mudah dipahami bahkan didebat karena tertuang melalui bahasa. Singkatnya dalam politik, bahasa menjadi sarana penting untuk mengekspresikan suatu gagasan.
Hal yang perlu diingat adalah bahwa bahasa dalam politik bukan sekadar pencitraan melainkan pergulatan paradigma. Bahasa diyakini mampu mengekspresikan hakikat terdalam dari diri manusia sebagai makhluk yang bereksistensi.
Ernst Cassier menjelaskan bahwa tindakan manusia selalu terdefinisikan melalui perilaku simbolik. Karena itu, perilaku simbolik tersebut bukanlah sekadar simbol-simbol tanpa makna, melainkan hal itu diyakininya sebagai usaha manusia untuk memberi arti mengenai hidupnya. Gudorf juga mengemukakan hal senada, yaitu bahwa kehadiran manusia dalam dunia dan dunia yang hadir dalam pikiran manusia tidak lain dikarenakan jasa bahasa.

Kesimpulan
Warga atau masyarakat adalah entitas sebuah bangsa karena itu para politisi harus menempatkan mereka bukan dalam relasi subyek-obyek, melainkan subyek-subyek. Jangan menganggap mereka sebagai potensi menuju kekuasaan, tetapi sebagai sebagai sebuah kekuatan membangun kejayaan bangsa dan negara.
Dengan begitu, dalam benak masyarakat timbul sense of belonging. Artinya, kemajuan sebuah kota bahkan bangsa Indonesia melulu bukan urusan pemimpin, melainkan urusan semua pihak.
Baca juga: Impian Indonesia Emas
Politik di negeri ini perlu dikembalikan kepada hakikatnya sebagai jalan menuju kebaikan bersama. Mobilisasi massa dan argumen yang bercorak hominen, yaitu suatu argumen yang dibangun atas dasar kebencian terhadap lawan politik dengan bahasa yang cenderung sarkatis dan penuh propanganda, harus kita akhiri.
Politik memang tidak lepas dari bahasa, tetapi letak efektivitas bahasa apabila sang pelaku dengan sadar dan sengaja melibatkan diri melalui perilaku. Dengan kata lain, bahasa menjadi sarana komunikasi yang mampu menyadarkan publik tentang tanggung jawab bersama mengelola bangsa dan negara.
Yulius Aris Widiantoro, Dosen di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia