G-20 Aroma ”Dangdut”
Keketuaan G-20 Indonesia jelas tidak ringan, tetapi sebagai konduktor Indonesia sudah sepantasnya memainkan musik dangdut, yang lebih dinamis dan memang mulai menggebrak dunia.
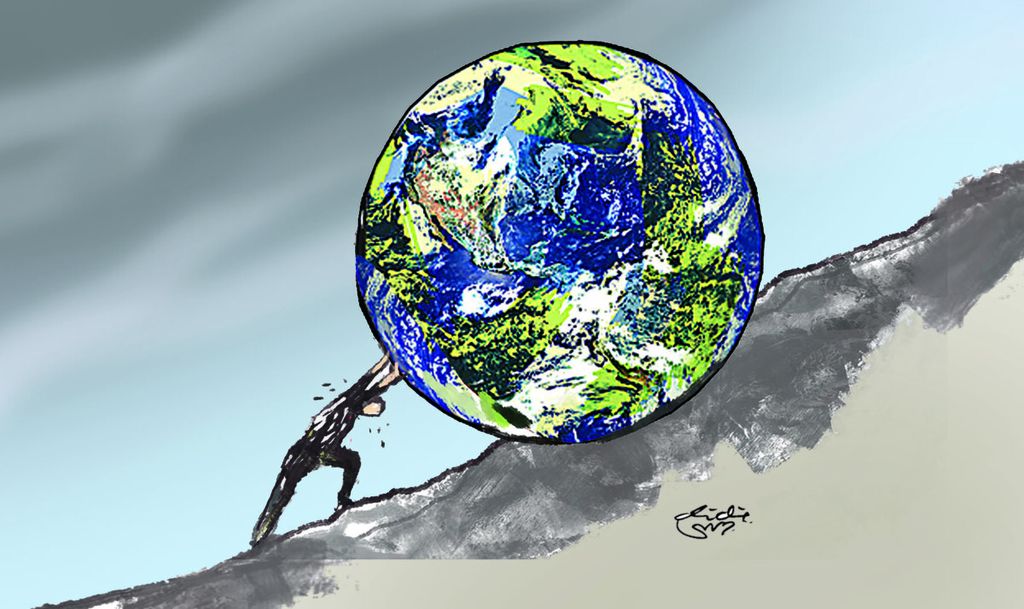
Didie SW
”Kegagalan” KTT G-20 pada 30-31 Oktober 2021 di Roma, Italia, menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia sebagai ketua kelompok negara ekonomi besar dunia ini untuk 2022.
Meskipun menghasilkan Deklarasi Roma, konferensi tingkat tinggi (KTT) itu dinilai gagal karena tidak menghasilkan langkah-langkah konkret, terutama dalam tiga isu utama (ekonomi global, energi, dan lingkungan hidup). Isu-isu itu pula di antaranya yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo dalam perhelatan besar tersebut.
Kegagalan di Roma bukan hanya masih lebarnya jurang antara negara besar-kecil, kaya-miskin, melainkan juga perbedaan tajam di antara negara besar dan kaya itu sendiri. Indikasinya sebenarnya sudah terlihat ketika Rusia dan China dari awal menyatakan tidak akan hadir. Hal ini menjadi lebih berat dengan ”kegagalan” KTT Perubahan Iklim PBB (COP 26) pada 1-2 November di Glasgow, Skotlandia.
Tantangan Indonesia juga semakin bertambah karena harapan masyarakat dunia terhadap forum ini sejak beberapa waktu belakangan ini mulai menurun. Menurut Thomas Wright dari Brookings Institution (Los Angeles Times, 31/10/2021), ”Dunia semakin terbelah (divided) karena terjadinya perbedaan (divergence) konstelasi antara negara-negara otoriter dan demokratis.”
Persaingan di antara negara-negara kuat, terutama Amerika Serikat (AS) dan China, telah menciptakan sinergi negatif (negative synergy), di mana masalah global bertambah, tetapi kerja sama untuk mengatasinya berkurang. ”Rich countries appear to be slingshotting out of the pandemic while others continue to suffer the economic aftershocks”.
Apalagi, tema yang diusung Indonesia ”Recover Together, Recover Stronger” yang jelas action oriented, dibandingkan dengan tema G-20 Roma ”People, Planet, Prosperity” yang lebih normatif.
Dua dasawarsa lalu (1999), forum informal para pemimpin ekonomi terbesar ini dinilai telah berhasil membawa dunia keluar dari krisis saat itu.
Harapan yang meredup
Dua dasawarsa lalu (1999), forum informal para pemimpin ekonomi terbesar ini dinilai telah berhasil membawa dunia keluar dari krisis saat itu.
Sebagai badan baru—yang menguasai 90 persen produk kotor dunia, 75-80 persen perdagangan internasional, dua pertiga penduduk dunia dan setengah wilayah daratan dunia—G-20 dinilai akan dapat mencegah kolapsnya ekonomi global. Forum ini juga dianggap sebagai inovasi yang penting menuju tata kelola global (global governance).
Awalnya perhatian G-20 difokuskan pada isu-isu utama dunia terkait ekonomi global, seperti utang luar negeri dan stabilitas keuangan global. G-20 tampil sebagai forum utama kerja sama ekonomi, menggantikan forum G-7 karena ekonomi global telah berubah signifikan dan peran ketujuh negara ekonomi besar itu telah karam.
G-7 tidak lagi dapat mendiktekan kebijakan global, sementara China dan kekuatan pasar yang baru tumbuh telah menjadi sangat penting sehingga perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai ekonomi global.
Setelah disahkannya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dan Persetujuan Iklim Paris (Paris Climate Agreement) pada 2015, kini G-20 menangani isu-isu prioritas, termasuk kemiskinan, lingkungan, kesehatan, energi, pendidikan, jender, pertumbuhan ekonomi, dan dana pembangunan.

Supriyanto
Namun, sejalan dengan dinamika perkembangan dunia yang pesat, semakin banyak pula tantangan dan hambatan yang ingin ditangani. Sejak saat itu juga keyakinan masyarakat dunia dan sebagian negara maju juga mulai meredup.
Menurut Thomas A Bernes dari Center for International Governance Innovation/CIGI (26/5/2020), penyebabnya adalah forum ini belum dapat keluar dari stigma memerangi krisis (crisis fighting) dan belum mengarah pada pengelolaan a forward-looking agenda. Karena itu, banyak yang menyatakan kegagalan ini tidak terhindarkan, tetapi ”menghibur diri” dengan mengatakan bahwa forum ini hanya efektif untuk menghadapi krisis global.
Masalahnya, krisis dewasa ini jauh lebih besar daripada krisis (finansial) pada 2008-2009, sementara respons G-20 ”adem ayem” (tepid) dan sangat tidak memadai untuk menjawab tantangan saat ini.
Baca juga : Presidensi G-20: Bukan Sekadar Giliran
Terlena musik klasik dan metal
Krisis Covid-19 pada awalnya diharapkan akan menjadi isu yang membangkitkan kembali kepemimpinan G-20 karena penanganannya hanya dapat dicapai berdasarkan upaya global. Ketika negara berkembang menderita karena tidak memiliki sistem kesehatan dan sumber daya fiskal yang memadai, negara-negara besar justru lebih fokus ke dirinya sendiri (inward looking).
Sementara negara-negara lainnya tak memiliki kapasitas kepemimpinan.
Dana Moneter Internasional (IMF), misalnya, hanya memberikan kesepakatan seadanya (minor tinkering) untuk membantu, dan WHO malah lumpuh akibat lambannya birokrasi dan dibekukannya kontribusi negara besar.
Menurut Bernes, krisis pandemi Covid-19 menunjukkan, kekuatan nasionalisme dan hilangnya kepercayaan (confidence) terhadap lembaga multilateralisme kini telah mendapatkan momentum baru.
G-20 perlu tidak hanya memikirkan reformasi global untuk keluar dari krisis, tetapi juga meyakinkan konstituen domestik bahwa kepentingan nasional akan meningkat dan bukan terancam dengan adanya sistem multilateral yang kuat. Reformasi kelompok ini juga diperlukan untuk mengurangi kelemahan (inertia) yang telah menjadi karakter selama satu dasawarsa.
Reformasi kelompok ini juga diperlukan untuk mengurangi kelemahan (inertia) yang telah menjadi karakter selama satu dasawarsa.
Dalam praktiknya, G-20 memang sarat dengan kepentingan nasional atau kelompok negara, terutama negara maju, dalam mengupayakan kesepakatan akhir. Hasil akhir suatu perhelatan global dalam kerangka PBB atau KTT semacam G-20, termasuk Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dari awal banyak ditentukan oleh negara-negara maju, yang notabene mencerminkan kepentingan mereka.
Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sering kali tidak siap memberi solusi yang inovatif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang lebih besar (dunia). Ibaratnya, hasil akhir perhelatan itu disusun (compose) atau diaransemen sesuai dengan aransemen musik klasik yang mendayu-dayu, tapi tiba-tiba terkaget-kaget oleh musik metal yang mengentak.
Negara berkembang yang terlena buaian program-program yang kelihatannya indah mendadak terentak dan terpaksa grusa-grusu (tergopoh-gopoh) mengejar sasaran yang ditetapkan. Ironisnya masyarakat dunia, termasuk Indonesia, begitu terpesona, bahkan bangga, ikut bergoyang (menyetujui) mengikuti iramanya dalam melaksanakannya, apalagi diiming-imingi bantuan (aid).
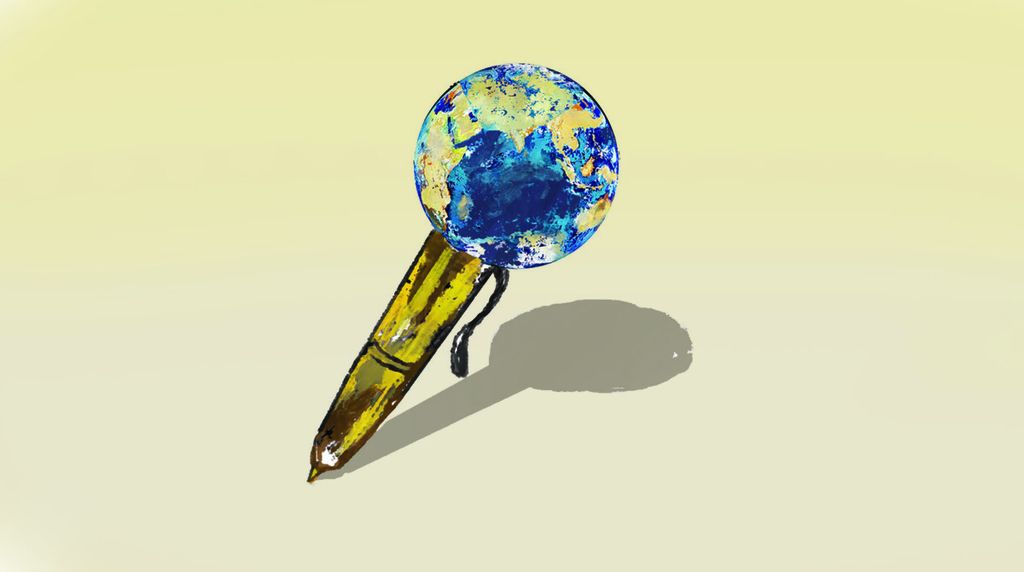
Didie SW
Dangdut lebih cocok
Kepentingan nasional bukan konsep utama dalam kebijakan luar negeri, melainkan merupakan pedoman bagi formulasi kebijakan itu. Menurut E William Collazier, dari Journal Science and Diplomacy (22/1/2021), bagaimana negara-negara merumuskan kebijakan luar negerinya akan memperlihatkan tujuan yang ingin dicapai dalam kerangka kepentingan global.
Dalam konteks ini, negara akan berpedoman pada kebijakan nasional ketika berkolaborasi dalam mencapai tujuan global. Dan sejauh mana persoalan-persoalan global diakomodasi dalam aspirasi nasional akan menentukan apakah mereka dapat mengatasi masalah-masalah global secara bersama-sama (”The degree to which global concerns are incorporated into national aspirations becomes one of the most important factors in determining whether countries can tackle worldwide problems together”).
Sebenarnya, hambatan dalam KTT G-20 Roma dan COP 26 Glasgow justru isu-isu yang jadi kepentingan utama Indonesia saat ini. Pertama, terkait pembatasan kenaikan suhu Bumi 1,5 derajat celsius dan target pengurangan emisi karbon, hanya dinyatakan, untuk menjaga agar tetap dalam jangkauan, diperlukan aksi dan komitmen yang ”meaningful” dan efektif.
Kedua, komitmen untuk mencapai emisi karbon net zero hanya dinyatakan sekitar pertengahan abad (mid century).
Ketiga, tidak adanya kesepakatan mengenai penghentian produksi batubara domestik, selain pernyataan formal untuk mengakhiri investasi dalam proyek-proyek asing.
Bahasa kompromi yang akhirnya disepakati di atas sebenarnya lebih cocok bagi Indonesia dan negara berkembang lain yang kaya sumber daya energi fosil.
Celakanya, China, India, Arab Saudi, Australia, dan Indonesia dianggap sebagai pengotor besar (big polluters). Padahal, menurut situs Climatetrade.com dan Statista (5/11/2021), sepuluh big polluters dunia adalah empat negara itu (minus Australia) ditambah AS, Rusia, Jepang, Jerman, Iran, dan Korea Selatan.
Sementara dalam kaitan dengan tambang mineral, Indonesia malah dituntut untuk tetap mengekspor batubara dan nikel (mentah), yang dikatakan untuk menjamin rantai pasok, tapi di lain pihak menggerogoti industri dan ekonomi nasional.
Pembahasan isu-isu itu pasti akan berlanjut dalam proses menuju KTT Bali. Bahasa kompromi yang akhirnya disepakati di atas sebenarnya lebih cocok bagi Indonesia dan negara berkembang lain yang kaya sumber daya energi fosil. Contohnya, dalam rumusan ”menghilangkan pemakaian batubara secara bertahap” (phase out) menjadi ”mengurangi setahap demi setahap” (phase down).
Sebagai negara utama produsen batubara, phase down jelas lebih cocok bagi Indonesia. Artinya, sebagian besar negara dunia, termasuk sebagian negara maju/kaya, memerlukan masa transisi yang belum tentu seirama.
Baca juga : Kepemimpinan G-20 Indonesia, Kesempatan yang Tak Boleh Meleset
Kesepakatan konkret bukan berarti harus ada kerangka waktu yang dipaksakan, apalagi didikte karena dari awal sudah dapat diperkirakan tidak akan dapat dicapai, seperti terjadi pada isu pengentasan warga dari kemiskinan dalam MDGs.
Time frame (kerangka waktu) harus fleksibel sesuai dengan kapasitas setiap negara secara umum. Pemaksaan akan membutuhkan teknologi, expertise, dan dana yang sangat besar, yang jelas sarat dengan kepentingan negara maju/Barat terhadap negara berkembang, yang cenderung akan melanggengkan ketergantungan.
Oleh karena itu, ”lagu” transisi perlu dimainkan dengan menggunakan musik dangdut, yang iramanya mendayu dan mengentak, menyatu secara harmonis.
Dalam keketuaan ini, Indonesia tetap harus mengedepankan kepentingan nasionalnya. Telah terbukti bahwa dengan ”musik” dangdut yang ngerem dan ngegas sesuai keadaan, Indonesia telah berhasil menangani Covid-19 secara efektif dan ekonomi tetap meningkat.
Sebelas bulan ke depan, Indonesia tetap perlu melaksanakan program-program prioritas G-20 dengan irama ini; ini pun merupakan kontribusi bagi dunia. Namun, perlu diingat, sebagai ”wakil” dan ujung tombak negara-negara berkembang, Indonesia berkewajiban memperjuangkan aspirasi mereka.

Dian Wirengjurit
Recover yang dimaksud dalam tema yang diusung Indonesia jelas bukan membalik tangan, melainkan memerlukan waktu dan kolaborasi. Keketuaan G-20 jelas tidak ringan, tetapi sebagai konduktor, Indonesia sudah sepantasnya memainkan musik dangdut, yang lebih dinamis dan memang mulai menggebrak dunia.
Dian Wirengjurit, Analis Geopolitik dan Hubungan Internasional