Ormas dalam Belenggu Kekuasaan
Sejarah dan pengaturan organisasi kemasyarakatan di Indonesia menghadirkan perdebatan dan tarik-menarik. Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari konteks dinamika politik serta saat diadopsi dalam undang-undang.
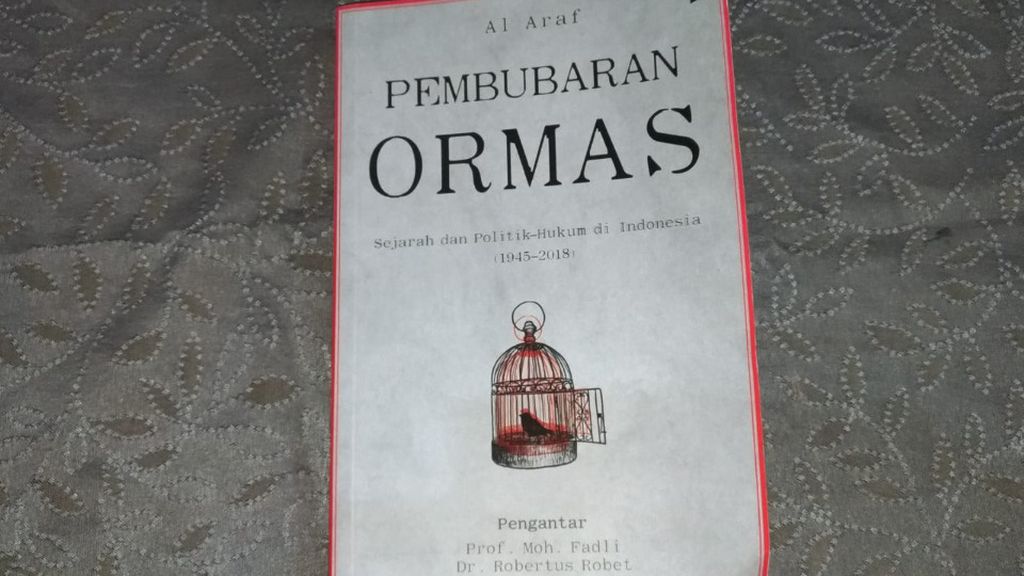
Halaman muka buku berjudul Pembubaran Ormas: Sejarah dan Politik-Hukum di Indonesia (1945-2018).
Judul: Pembubaran Ormas: Sejarah dan Politik-Hukum di Indonesia (1945-2018)
Penulis: Al Araf
Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia
Tahun terbit: 2022
Jumlah halaman: xxx + 362 halaman
ISBN: 978-602-481-784-8
Sejarah dan pengaturan tentang organisasi kemasyarakatan di Indonesia selalu menghadirkan perdebatan dan tarik-menarik. Hal ini terjadi antara posisi politik negara yang menginginkan kontrol masyarakat dan posisi politik masyarakat yang mendorong adanya ruang kebebasan. Perdebatan dan tarik-menarik tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks dan dinamika politik yang berkembang, termasuk saat diadopsi dalam undang-undang.
Pengaturan tentang organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Secara argumentatif Al Araf dalam Pembubaran Ormas: Sejarah dan Politik-Hukum di Indonesia (1945-2018) (KPG, 2022) menerangkan bahwa pengaturan organisasi kemasyarakatan cenderung terjadi karena nalar politik kekuasaan mengarah pada kontrol pemerintah terhadap entitas kelompok masyarakat sipil. Akibatnya, muncul ormas-ormas binaan penguasa yang menjadi perantara dan pengaman kepentingan politik dan ekonomi-bisnis.
Pengaturan ormas tidak lagi dilakukan untuk pemenuhan hak atas berserikat dan berorganisasi, di mana ada hak setiap orang untuk membentuk, memilih, atau bergabung dengan organisasi yang sesuai dengan hati nurani; atau untuk perjuangan tujuan dan kepentingan bersama.
Bukan hak absolut
Sebagai negara demokrasi yang menghormati prinsip-prinsip negara hukum, pengaturan ormas, termasuk pembubaran, seharusnya tidak mengancam kebebasan berserikat dan berorganisasi. Hak atas kebebasan tersebut tidak hanya esensial bagi individu dan masyarakat, tetapi juga menjadi komponen penting demokrasi di sebuah negara. Bahkan, kebebasan dalam berserikat dan berorganisasi menjadi sebagai salah satu jantung dari demokrasi karena terkait erat dengan kebebasan dan hak asasi lainnya, seperti kebebasan berpendapat, berekspresi, berkumpul, berpikir, beragama, dan berkeyakinan. Kebebasan ini berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia, baik itu hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Namun, kebebasan berserikat dan berorganisasi bukanlah hak asasi yang bersifat absolut. Dalam konteks HAM, kebebasan berserikat tidak termasuk hak yang tidak dapat dibatasi.Pemerintah dapat melakukan pembatasan atas kebebasan ini, termasuk tindakan yang paling ekstrem adalah pembubaran. Hal yang menjadi penting, tindakan tersebut tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan merupakan pilihan paling akhir serta harus memenuhi prinsip legalitas (legality), kebutuhan (necessity), dan proporsional (proportionality).
Kenyataannya, kebijakan terkait dengan kebebasan berserikat dan berorganisasi tampaknya masih terikat pada negara dan kekuasaan.
Pembubaran ormas
Pengaturan organisasi masyarakat di Indonesia masih menggunakan paradigma pembatasan dan kontrol negara yang lebih dominan (otoriter) ketimbang berpijak pada kehidupan negara demokrasi, di mana perlindungan kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin. Paradigma yang melatarbelakangi cara pandang penerbitan UU Ormas selama ini cenderung melihat masyarakat sebagai sumber ancaman, sumber konflik sosial, dan bahkan sumber disintegrasi bangsa. Padahal, dalam negara demokratis, masyarakat adalah sumber legitimasi bagi keabsahan keberadaan negara dan pemerintahan yang dihasilkan oleh pemilu yang demokratis. Masyarakat dan organisasi masyarakat memiliki peran penting dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
Pada masa Orde Baru, pengaturan organisasi kemasyarakatan lebih menonjolkan paradigma yang mengontrol masyarakat ketimbang memberikan jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul. Pengaturan tentang ormas yang hadir di masa Orde Baru melalui UU No 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak bisa dilepaskan dari visi politik rezim yang ingin melanggengkan kekuasaan sehingga ruang gerak masyarakat perlu diatur, dikontrol, dan dibatasi.
Pembuatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 kental dengan dimensi politik, di mana penetrasi negara kepada masyarakat terlalu dalam dengan alasan menjaga stabilitas. Akibatnya, semua organisasi masyarakat harus tunduk kepada pemerintah. Paradigma kontrol negara terhadap masyarakat saat itu merupakan paradigma berpikir yang otoriter.
Pada masa Reformasi, pengaturan tentang organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam UU No 17/2013 sebagai bentuk revisi terhadap UU No 8/1985 sepertinya belum dapat keluar dari paradigma pembatasan dan kontrol negara terhadap masyarakat. Pembentukan UU No 17/2013 memiliki kesamaan visi dengan pembentukan UU No 8/1985 oleh rezim Orde Baru, yang melihat masyarakat sebagai ancaman sehingga perlu dikontrol. Ormas-ormas yang ada dinilai banyak yang tidak patuh kepada pemerintah sehingga diperlukan undang-undang yang baru.
Negara sebagai penguasa memandang ormas sebagai sebuah kelompok dalam negara yang tidak boleh menjadi kelompok penekan terhadap pemerintah karena mengganggu jalannya pemerintahan.Pembentukan undang-undang ini secara tersirat masih mengedepankan aspek kontrol negara terhadap masyarakat serta tidak memberi jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul. Kondisi ini bertolak belakang dengan semangat demokrasi yang menginginkan adanya kontrol dan partisipasi masyarakat terhadap kekuasaan. Sebab, partisipasi dan kontrol masyarakat penting untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
Aturan tentang ormas dalam UU No 17/2013 juga bersifat ambigu. Di satu sisi memberi ruang kepada pengadilan untuk membubarkan ormas yang berbadan hukum, di sisi lain memberi ruang kepada pemerintah untuk membubarkan ormas yang tidak berbadan hukum tanpa melalui proses peradilan. Alasan pembubaran ormas juga menjadi lebih kompleks dan multitafsir. UU Ormas tidak sepenuhnya menghormati prinsip negara hukum secara penuh. Namun, mekanisme pembubaran ormas berbadan hukum diatur dengan lebih baik, yakni berjenjang sebelum tahap pembubaran melalui pengadilan.
Paradigma pembatasan dan kontrol negara terhadap masyarakat ini terus berlanjut ketika pemerintahan Joko Widodo membuat Perppu No 2/2017 yang kemudian disahkan menjadi UU No 16/2017. Mekanisme pembubaran ormas dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah dengan berbagai alasan pembubaran yang bersifat lentur dan multitafsir.
Aturan tersebut dinilai mencerminkan visi politik negara yang otoriter, di mana pemerintah mengabaikan mekanisme hukum peradilan (due process of law) untuk membubarkan ormas. Pemerintah merasa kelompok-kelompok yang dianggap mengganggu jalannya kekuasaan sebagai ancaman sehingga dapat dibubarkan.
Paradigma pengaturan tentang ormas di alam demokrasi sudah seharusnya berpijak pada kaidah-kaidah negara hukum demokratis yang menjamin perlindungan kebebasan berserikat dan berkumpul. Sanksi berupa pembubaran ormas semestinya menjadi pilihan terakhir setelah semua langkah persuasif dan dialogis dilakukan. Mekanisme pembubaran ormas pun semestinya melalui peradilan, bukan oleh pemerintah. (Litbang Kompas)